Menjadi seorang guru les merupakan salah satu pekerjaan (profesi) yang banyak dilakoni oleh mahasiswa, terutama mahasiswa peraih Bidikmisi, yang kebanyakan mencari tambahan biaya untuk agar tetap bisa bertahan hidup dan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini profesi yang menyenangkan, sebagai menjadi bagian yang bisa mendidik generasi dan menjadikan pelajar bagi para pembelajar.
Sebagai pelajar, idealnya yang mereka lakukan ya belajar. Bukan hanya sekolah. Namun di sekolah, anak-anak itu tidak merasa banyak belajar. Metode pembelajaran yang ada tampaknya menuntunnya untuk hanya mampu menghafal, bukan memahami. Disinilah ketika di kelas les, guru les harus menjelaskan lagi konsep pembelajaran dari awal, padahal materi tersebut sudah diterangkan oleh guru di sekolahnya.
Jadi, yang dilakukan hanyalah transfer knowledge, bukan transfer pemahaman. Mereka hanya di-drill untuk lulus UN (Ujian Nasional), sehingga tidak menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Alhasil tujuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas 2003 pasal 3 yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, tampaknya hanya akan menjadi slogan semata.
Beberapa orang tua sengaja memberikan les tambahan pada anak-anaknya, karena menyadari dirinya punya keterbatasan, sehingga merasa perlu untuk menitipkan buah hatinya agar memiliki pengetahun yang lebih di tempat les, karena pendidikan di sekolah belum cukup untuk mengasah potensi anak mereka. Pada sisi lain, para orang tua itu sebenarnya bergelar sarjana, tetapi tidak memiliki waktu untuk mendidik anak dan mengevaluasi proses belajar anak di sekolahnya.
Dari kesibukannya itulah banyak ibu yang menyerahkan pengasuhan dan pendidikan anaknya kepada pembantu, tetangga, dan nenek mereka. Masalah ekonomi ikut mempengaruhi disini, sebab kebutuhan ekonomi yang sulit memaksa para orang tua, termasuk para ibu, meninggalkan peran keibuannya dan bekerja keras diluar rumah.
Sebagai guru les akhirnya harus berperan layaknya ibu bagi mereka, tempat curahan keluh kesahnya di sekolah, mencurahkan keinginan dan cita-citanya, tentang gurunya, teman-teman, dan tak jarang juga mengeluhkan kesibukan orang tuanya yang tidak sempat menanyakan sekedar: ”bagaimana nilai ulanganmu hari ini?”.
Hal-hal seperti itu banyak kita jumpai dalam kelas-kelas les. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, justru menjadi sarana untuk melampiaskan rasa protes terhadap kondisi lingkungan keluarga, sekolah yang amburadul, ada guru mengajar asal-asalan, buku paket yang banyak rusak, dsb. Bisa jadi, adanya pelajar yang amburadul itu karena besar di lingkungan keluarga/sekolah yang juga amburadul. Disana tidak ada panutan, tidak ada arahan, tidak ada contoh keteladanan dan pendampingan.
Sudah banyak kasus dari bobroknya output pendidikan seperti itu. Generasi pembelajar mengalami degradasi moral, seperti yang terjadi pada pasca Unas 2015 dimana pelajar tak lagi coret-coret di baju seragamnya dan konvoi kendaraan, namun juga terjadi kasus perzinaan masal, tawuran dan perbuatan maksiat lainnya. Di Siantar, misalnya, seusai Unas ratusan siswa bersuka-ria mencorat-coret bajunya, bahkan beberapa siswa melakukan aksi-aksi asusila. Di Purwakarta (Jawa Barat) dua kelompok siswa diamankan polisi karena melakukan tawuran. Kemudian di Kendal (Jateng), masih pasca Unas, puluhan pelajar tertangkap basah berbuat mesum di sebuah kamar hotel. Belakangan kita dihebohkan dengan tersebarnya undangan “pesta bikini” bagi anak SMA usai pelaksanaan Unas yang bertajuk “Good Bye UN”.
Mengkaji dari peristiwa diatas kita tidak bisa menutup mata bahwa secara rata-rata sistem pendidikan belum menghasilkan generasi unggul. Seandainya negeri ini memiliki visi politik yang jelas terhadap pendidikan, tentu hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Kegagalan melahirkan output bermoral dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, disinyalir terkait dengan kapitalisme yang merangsang biaya pendidikan semakin mahal. Kapitalisme inilah konon yang ikut membuat kaum perempuan terpaksa meninggalkan perannya sebagai ibu demi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Kondisi seperti ini mungkin saja akan menjadi semakin parah jika kita diamkan dan membiarkan keadaan. Jadi kesalahan ini harus diluruskan. Pertama, pendidikan adalah kebutuhan pokok rakyat karena setiap warga negara berhak memperoleh akses pendidikan. Hal ini tentu sangat bisa dipahami karena maju-mundurnya suatu peradaban sangat bergantung pada kualitas pendidikan manusianya.
Kedua, output pendidikan berupa generasi bertakwa yang unggul pada seluruh aspek kehidupan, menuntut perhatian serius dari kompenen terkait yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, yang kondusif serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Ketiga, untuk mewujudkan hal itu negara harus memiliki sistem ekonomi yang kuat, karena kedua hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Dengan potensi sumber daya alam yang kuat, tentu negeri ini memiliki pemasukan yang besar untuk bisa mewujudkannya, asalkan SDA itu dikelola dengan benar yaitu menjadikan aset hajat hidup publik milik rakyat dikelola oleh negara. Satu misal dari Blok Mahakam saja berpotensi menghasilkan pendapatan kotor Rp 1.700 triliun, sehingga jika kita memiliki 79 blok migas, tentu ini merupakan sumber APBN yang diharapkan juga bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat. Hal demikian tentu tidak akan terwujud jika paradigma ekonomi neoliberal yang menjadi rujukan dan hajat hidup publik diprivatisasi dan dimiliki asing yang menyebabkan negeri ini terjerat dalam penjajahan gaya baru (neoimperialisme).
Semoga sedikit curahan hati ini menjadi inspirasi untuk tidak henti-hentinya menjadikan pendidikan di negeri ini lebih baik. Potensi optimalisasi generasi muda sebagai aset berharga bangsa menjadi kenyataan, dan terlahir jutaan intelektual hebat dengan penghargaan luar biasa dan mampu mewujudkan peradaban gemilang mercusuar dunia.

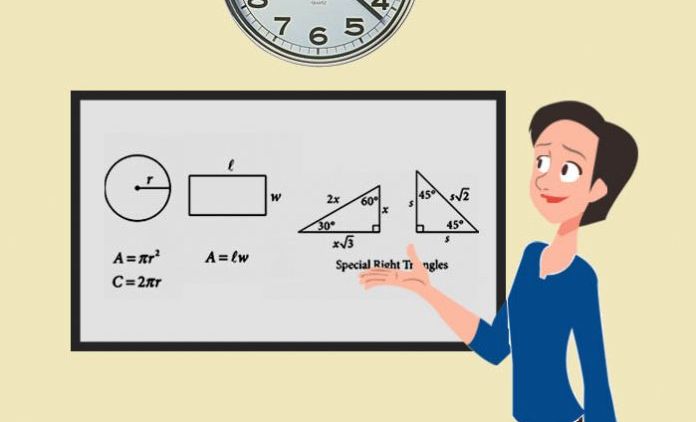












Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.