"Aku tidak takut!"
Teriakan hati milik mahasiswi Psikologi itu terdengar begitu lantang. Ia memang ingin bertutur tegas kepada penduduk bumi yang kala itu sedang bersembunyi di bawah atap yang nyaman, pun di atas kasur yang empuk.
Menegaskan bahwa guyuran hujan, teriakan petir, pun sambaran kilat, bukanlah misbehavior of earth yang layak untuk ditakuti.
"Mereka turun ke bumi untuk menantang. Dan hanya jiwa-jiwa pemberanilah yang akan merasa tertantang," tegasnya pelan; di dalam benda kecil, bernama hati.
***
"Aku tidak takut! Aku akan tetap pergi!"
Gaungan hati milik perempuan ber-ransel hitam itu kembali menggelegar. Makin keras. Makin tegas.
Ia memang keras kepala. Lagi-lagi ia ingin bertutur tegas kepada makhluk-makhluk yang pada saat itu sedang berselimut, bahwa derasnya hujan, kerasnya petir, pun bengasnya kilat, bukanlah alasan untuk tetap berteduh di balik selimutnya yang tebal dan empuk. Ya, sore kemarin, perempuan rantau itu kembali berulah. Perempuan rantau itu, ah, sebut saja dia, "aku".
***
Sore kemarin. Saat hembusan angin senja memercikkan air langit yang hendak membasahi tanah Tembalang. Saat jiwa-jiwa sang perantau menelingkup di balik selimut tebal nan empuk, menyambut virus kantuk yang tiba-tiba menusuk sebab terang tak kunjung datang. Saat-saat itulah aku, si perempuan berjaket merah, ber-ransel hitam, penenteng tas cangkingan berisi beberapa buku cerita roman, berdiri di depan pintu yang bertuliskan "Kamar 304 Graha Larasati" dan berucap lantang, "Bu, kini ku penuhi janjiku. Aku pulang! Tak peduli, meski bumi sedang tak karuan."
Sekali lagi ku lirik seisi kamar; memastikan tidak ada yang tertinggal, lalu mengunci pintu, dan turun menuju lantai dasar.
Dug.
Langkahku terhenti di suatu ruangan luas berisikan 17 kendaraan roda 2 berjenis matic. Tak selang lama, salah satu kendaraan berwarna merah merona, dan ber-body ramping melambaikan tangan ke arahku. Rupanya ia telah siap bertamasya ria dengan pemiliknya. Aku pun segera mendekat. Membunyikan mesinnya, memberinya kesempatan untuk melakukan pemanasan semenit saja, lalu bergegas tancap gas. Ya, tepat pukul 17.30 aku meluncur ke jalanan. Berbaur bersama hujan. Asik, 'kan?
***
Musim penghujan memang menyebalkan bagi mereka yang hobinya motoran. Tapi tidak dengan perempuan pembuat onar ini.
Kau tahu? Dulu aku sempat dikeroyok habis-habisan oleh angin kencang, hujan lebat, pun gelap malam. Terlunta-lunta di jalanan karena satu-satunya jembatan pengantarku ke tujuan (rumah) tidak bisa dilewati.
Para rider kebanjiran. Pun kebingungan mencari jalan agar sampai ke tujuan. Dan alhasil, sampai rumah aku jendindilan (semacam penyakit tak butuh obat yang diakibatkan oleh kedinginan akut dan bisa sembuh kalau ada selimut). Dan kau tahu, di mana letak ke-onar-an-ku? Aku membuat semua orang kesakitan. Teridap penyakit khawatir yang tak ketulungan.
Ahh. Barangkali mereka yang terlalu lebay memaknai kehilangan, atau aku yang kelewatan? Toh aku tak lantas hilang? Toh aku masih selamat sampai tujuan? Tak terbawa badai yang menghantui saat masih di jalanan.
Dan kamu tahu? Sore kemarin, aku mengulanginya. Kembali pulang dengan hujan dan gelap malam. Berharap di tengah perjalanan langit akan terang benderang, sehingga banjir kala itu tak akan terulang.
Haha. Aku suka. Sangat suka.
Berkendara sendirian. Kala malam bersama hujan. Asyik, bukan?
Butiran air langit yang menemaniku di awal perjalanan memang tidak terlalu deras. Hanya gerimis, yang sesekali lebat. Aku masih bisa menyetir santai sambil satu-dua kali melirik ke kanan dan kiri. Menikmati suasana Tembalang di kala senja, untuk terakhir kalinya, sebelum angka tahun bertambah usia.
*** Di sepanjang jalan, sembari menonton apa-apa yang ada di jalanan, aku mencoba mengkondisikan pikiran agar tak tersangkut-sangkut. Tapi sialnya, usahaku menonton pikiran selalu saja gagal.
Berkali-kali ku coba mengkondisikan pikiran-pikiran yang berdatangan layaknya iklan. Membiarkan mereka datang, mampir sebentar, lalu kembali pulang. Tapi usahaku sia-sia. Sebuah pikiran bernama was-was meraung-raung tak mau pulang.
Ya, aku memang sedikit was-was. Kepikiran kalau di tengah perjalanan, hujan menjadi lebih lebat dari yang ku bayangkan. Sedangkan aku hanya berbekal jaket angkatan warna merah yang tebalnya tak sampai satu senti. Jas hujan? Haha. Sempat terpikir dalam benak untuk mampir ke toko, membelinya. Tapi, karena uang lembaran di dompet tinggal beberapa, habis untuk belanja di Gramedia kemarin, jadi kuputuskan untuk tidak jadi beli.
Haha. Kewas-wasanku itu tidak berlangsung lama. Sebab tak lama dari itu, pikiran-pikiran baru bermunculan, mendesak pikiran bernama was-was untuk keluar. Tepatnya, ketika terdengar suara merdu milik para muadzin, mengumandangkan adzan Maghrib. Bersaut-sautan antara surau satu dengan surau lainnya. Aku pun memperlambat laju kecepatan (agar tidak kualat saat di jalan).
***
Hembusan angin senja yang terasa adem sekali, dibarengi lantunan suara merdu milik muadzin yang entah siapa, membuatku terbawa suasana. Suasana itu membawa pikiranku untuk mundur beberapa langkah ke belakang. Mengingat-ingat perbincangan hangat yang terjadi beberapa waktu lalu di suatu majelis ilmu.
Pada perbincangan itu, aku dan beberapa anggota majelis lainnya mengikrarkan sebuah janji. Kami berjanji untuk membiasakan diri menikmati adzan. Kami berjanji untuk berhenti dari aktivitas apapun setiap kali mendengar suara adzan. Lalu meresapi setiap lantunannya, pun mengkondisikan diri untuk berada dalam keadaan mindfulness; kondisi di mana Anda memiliki kesadaran penuh dan atensi yang tinggi atas apa yang Anda alami, rasakan, pikirkan, pun hal-hal yang terjadi di sekeliling Anda, pada suatu waktu (Zahra, 2017).
Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan.
Kemudian bershalawatlah untukku. Karena barangsiapa yang bershalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.
Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di Surga yang tak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barangsiapa memintakan untukku wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapat syafa’atku.
-Rasul SAW
Setidaknya di perjalananku kali ini, bukan hanya dingin yg ku dapatkan. Melainkan kesadaran bahwa ada yang lebih nikmat dari mendengarkan musik saat sedang dijatuhcintakan. Yaitu MENDENGARKAN & MENIKMATI ADZAN, saat berkendara, di kala senja, bersama hujan. Sungguh! Percayakan? ?
***
Berkendara di malam hari memang mengerikan bagi sebagian orang. Seperti suasana di jalan yang ku lalui setelah seperlima perjalanan. Jalan itu memang bukan jalan raya. Pantas saja, jarang ada kendaraan roda 6 yang melaju di atasnya. Tapi suasana seperti itu sangat menguntungkanku. Aku jadi bisa lebih leluasa berkendara. Menambah laju kecepatan pun bisa dihukumi aman-aman saja.
Sembari membiarkan roda motor bergelinding dengan laju yang sedikit lebih cepat, aku membiarkan pikiranku berkelana. Ia berkelana ke Taman Cinta. Tak jauh berbeda dengan tempat yang k ukunjungi di perjalananku sebelumnya. Entah mengapa, tiap kali aku berkendara sendirian, pikiranku selalu saja melesat ke sebuah taman bernama Cinta. Padahal aku tahu persis, pada akhirnya aku akan terluka. Sebab ada rindu di dalamnya. Rindu yang membuat memar ulu hati. Membuat nyeri tak kunjung berhenti. Tapi tetap saja, tiap kali aku berkendara, imajinasiku selalu saja tak pernah bosan mengunjunginya. Entahlah, mengapa..
***
Tempat itu bernama Taman Cinta. Taman megah yang hanya dihuni oleh 2 manusia biasa. Seorang putri kecil manja dan seorang lelaki paruh baya yang bijaksana. Mereka memang hanya berdua saja. Tapi tawa putri kecil itu tak pernah ada habisnya. Rupanya, lelaki paruh baya itulah sumber bahagianya.
Pernah suatu hari, sang putri kecil pergi meninggalkan taman. Ia pergi mengelilingi jagat raya untuk bertamasya bersama teman-temannya. Bahagia luar biasa pun terpancar di parasnya. Pasalnya, itu kali pertama ia pergi dari istana seorang diri. Bukan hanya pergi ke seberang jalan, tapi ke beberapa kota nan jauh di sana. Tempat demi tempat ia kunjungi. Menyusuri desa, hingga kota. Menapaki jalan sempit menghimpit, hingga jalan raya yang luar biasa luasnya. Dan di perjalanan itu lah ia menyadari bahwa dirinya sudah beranjak dewasa. Bukan lagi menjadi gadis kecil nan manja.
Setelah puas bertamasya, ia pun bertekad untuk menjadi pribadi mandiri. Ia memberanikan diri untuk meminta izin kembali ke taman seorang diri. Ia tidak ingin lelaki paruh baya itu kerepotan menjemputnya. Ia ingin pulang sendiri. Seorang diri. Akan tetapi permintaan izinnya tak diterima. Lelaki paruh baya yang setengah mati mencemaskannya itu, benar-benar tidak tega membiarkan sang putri kecil menempuh perjalanan jauh tanpa ada yang mendampingi. Ia takut putrinya kenapa-napa. Ia takut kalau putri kecil itu kedinginan di jalan, kelelahan, pun kalau-kalau tersesat dan tak tahu jalan pulang.
Ya, lelaki paruh baya itu memang sangat mencintai sang putri kecil. Ia tetap saja menjadi bayang-bayang tiap kali putri kecilnya pergi, meski putri kecil itu berkali-kali bilang bahwa dirinya bukan anak kecil lagi.
Sang putri kecil sudah beranjak dewasa. Tapi lelaki itu tetap saja mengikuti tiap langkahnya.
Atau barangkali itu yang namanya cinta? Cinta dari laki-laki biasa untuk buah hatinyakah?
Jikalau itu yang disebut cinta, cinta dari seorang laki-laki biasa, maka ketahuilah: Cinta itu sungguh menguras kalbu. Menyulam hatiku dengan rindu. Rindu menggebu, kala si putri kecil tak bisa lagi bertemu (dengan lelaki paruh baya itu). Sungguh, cinta itu benar-benar menyuras hatiku.
***
Hatiku? Ya. Sebut saja putri kecil itu "aku". Dan lelaki paruh baya itu, anggap saja dia, ayahku. Ayahku yang sungguh menyayangiku.
Ayahku, yang sangat benci melihat putri kecilnya kehujanan, sendirian, di kala malam.
***
Aku suka. Sangat suka. Berkendara sendirian. Kala malam bersama hujan. Asyik, bukan?
Taman Cinta. Itulah mengapa; aku suka berkendara saat hujan.
Ya, aku sangat suka hujan. Hujan memberiku ruang untuk meluapkan rindu. Leluasa meluap, tanpa seorangpun tahu, bahwa yang mengalir membasahi pipi ialah air yang bermuara dari rindu. Dari mata hatiku. Bukan air hujan dari langit itu. Karena itulah mengapa aku suka hujan.
Sebab hujan menenangkan. Sebab hujan memberi kesejukan, pada tiap hati yang kehausan.
***
Aku suka. Sangat suka. Berkendara sendirian. Kala malam bersama hujan. Asyik, bukan?
Hembusan angin yang makin lama makin kencang, diiringi suara petir yang membisingkan pendengaran, membuat suasana Pantura semakin mencekam. Aku mulai menggigil. Tubuh sudah penuh dengan air. Tak menyisakan setitik ruang pun yang kering. Ingin menepi, berteduh menghangatkan diri, tapi tak jadi.
Lagipula untuk apa? Toh perjalanan masih panjang. Bumi Kartini masih 75 kilometer lagi. Suhu tubuh yang terasa sudah berada di minus sekian derajat celcius pun tak akan bertambah naik bila ku tepikan kendaraanku untuk berteduh.
"AKU KUAT. AKU HEBAT! AYO SEMANGAT!" teriakku dalam hati, menyemangati raga yang kian mengkerut pun kulit yang kian keriput, karena kedinginan.
***
Aku meneruskan perjalanan. Ku percepat laju kendaraan, tapi dengan penuh kehati-hatian. Kecelakaan yang ku saksikan di jalanan yang ku lewati beberapa kil meter sebelumnya, cukup membuatku trauma dan jauh lebih waspada.
"Oh, God. Aku tak mau jatuh konyol seperti pemuda itu," gerutuku seraya menguatkan tubuh yang ingin pingsan karena kedinginan.
Angin kencang yang menggoyangkan pepohonan membuat listrik berhenti menerangi jalanan. Listrik seketika padam. Hanya rembulan dan lampu-lampu kendaraan yang menerangi jalan. Aku pun memperlambat laju kendaraan. Ku lihat kanan-kiri. Satu, dua bangunan yang ku lalui tampak gelap gulita, nyaris seperti rumah tak berpenghuni. Aku mulai gemetaran. Bukan karena ketakutan, tapi karena kedinginan yang terus-terusan menjalar. Aku mencoba tenang. Ku posisikan sorot mataku lurus ke depan, lalu ku coba menikmati perjalanan.
***
Tak lama dari itu, tetiba saja, mataku terbelalak. Menyoroti seorang lelaki bergamis putih yang berdiri di tepi jalan, persis beberapa meter dari hadapan. Ia melambaikan tangan ke arahku. Seperti ingin meminta tumpangan, atau menawarkan jas hujan? Haha.
Entahlah. Kala itu aku tak berpikir panjang. Ku arahkan roda kendaraanku ke tepi jalan, lalu ku berhentikan tepat di depannya.
***
"Bolehkah aku menemani perjalananmu, nak?" tanyanya yang membuatku tak bisa menolak.
Ternyata ia seorang lelaki paruh baya yang berusia kurang lebih 50-an. Ia tak membawa apapun, kecuali sebuah payung dan jaket tebal yang kemudian diberikan kepadaku. Bapak itu kelihatannya baik, sama sekali tidak ku temui tampang penjahat di parasnya. Aku hanya manggut-manggut dan sedikit senyum. Setelah ku kenakan jaket yang beliau berikan, kami pun melanjutkan perjalanan.
"Bapak dari mana, dan mau ke mana?" tanyaku mengawali pembicaraan. "Saya musafir, nak. Perjalanan saya masih panjang," jawab beliau singkat.
"Memangnya bapak mau ke mana?" tanyaku lagi. "Saya penduduk Negeri Cinta, nak. Di sana ada Taman Surga yang megahnya luar biasa," jawabnya yang membuatku semakin penasaran.
"Memangnya, ada apa saja di sana? Apakah saja boleh mengunjunginya?" "Taman Surga adalah taman yang penuh kebahagiaan. Di sanalah tempat bagi para perindu."
"Perindu????"
"…."
Percakapan itu mengalir begitu saja. Panjang, sepanjang jalan Pantura. Aku jadi memahami satu hal, bahwa perjalanan panjang akan terasa lebih menyenangkan bila tak sendirian. Bahwa perjalanan panjang akan lebih membahagiakan bila dilalui dengan berduaan, bersama hujan. Haha.
***
Bapak bergamis putih itu bercerita kepadaku tentang banyak hal. Tentang Negeri Cinta, yang di sanalah surga bagi para pecinta-Nya. Tentang Taman Surga, yang di sanalah tempat berkumpulnya para perindu.
Perindu???? Termasuk perindu-kah aku??
"Saya juga perindu, pak. Saya perindu yang merindukan sosok panutan yang telah lama pergi. Saya teramat merindukannya, sampai-sampai saya berharap ia akan menghampiri saya. Menemani saya setiap kali saya sendirian. Saya teramat merindukannya, ia yang sangat khawatir ketika buah hatinya kehujanan, sendirian. Ya, ia sangat memerhatikan saya. Apapun yang saya lakukan, dan ke manapun saya pergi, ia selalu tahu, ia selalu ada. Ia memang sangat memanjakan saya, pak. Tapi jangan salah, ia adalah sosok yang sangat tegas. Luar biasa tegasnya. Tak semua yang saya mau akan ia turuti segera. Tak semua permintaan saya akan ia kabulkan seketika. Ia mengajari saya untuk berjuang dahulu, sebelum keinginan saya terpenuhi. Ia mengajari saya untuk tetap bangun sendiri, makan sendiri, apa-apa sendiri, meskipun tubuh meriang tak ketulungan. Merengek? Haha, ia tak pernah mengajari saya demikian. Ia memang penyayang, pak. Tapi bukan berarti apapun yang saya minta segera di-iya-kan. Dan ketika ia pergi, saya baru menyadari arti dibalik sikap kerasnya. Pun arti di balik ketegasannya. Ya, saya benar-benar baru menyadari, bahwa ada milyaran arti dibalik sikap tegas ayah. Saya sangat merindukannya, pak. Teramat sangat. Lalu, apakah saya ini termasuk salah satu dari para perindu yang berhak menghuni Taman Surga itu?"
Adakah yang lebih menyakitkan dari rindu?
Rindu yang tiada penawarnya, selain pertemuan dalam angan. Mimpi-mimpi yang sesekali, dan doa-doa yang senantiasa.
Adakah yang lebih menyakitkan dari rindu?
Rindu yang sesaknya bukan sekedar ketika kau putus cinta. Disuapi ribuan janji, dijatuh-cintakan setengah mati, lalu ditinggal pergi. Bukan. Ini bukan sekedar ketika kau patah hati.
Adakah yang lebih menyakitkan dari rindu?
Rindu yang tak memungkinkan adanya pertemuan. Seperti lautan yang merindu awan. Seperti kemarau yang merindu hujan.
Seperti mereka, yang meradang rasakan rindu, tapi tak bisa bertemu.
Adakah yang lebih menyakitkan dari tak bisa bertemu?
ADA????
"ADA. Hanya saja, kau belum pernah merasakan. Belum terlalu kenyang makan asam-garam. Belum dikasihtahu, bahwa kehilangan bukanlah satu-satunya hal yang paling menyakitkan. Bukan.
Lalu apa? Lalu kau hanya perlu menikmati hidupmu. Tak perlu bertanya-tanya atau menerka-nerka. Mengapa? Sebab kelak kau akan tahu sendiri. Seiring dengan bertambahnya usiamu. Seiring dengan dewasanya pikirmu. Seiring dengan makin lapangnya hatimu. Kau akan tahu. Bahwa, ada yang lebih menyakitkan dari rindu, ada yang lebih menyakitkan dari tak bisa bertemu. Ada."
Seperti lautan yang merindu awan, barangkali begitulah rinduku. Yang meradang, karena kehilangan.
"Siapa yang lebih kau rindukan, nak? Apakah kerinduanmu pada ayahmu, jauh lebih besar dari kerinduanmu akan surga Tuhan?"
"Tentu saja, saya lebih merindukan ayah saya, pak. Bahkan saya jarang sekali berbicara tentang surga."
"Mengapa, nak?"
"Sebab dahulu ketika saya kecil, saya pernah bilang pada ayah bahwa saya mau rajin salat agar bisa menjadi penghuni surga. Kala itu aku sangat terobsesi pada surga, jadi kupikir, tujuan beribadah adalah demi mengharap surga. Tapi ayah menasihatiku. Beliau bilang bahwa tujuan beribadah bukanlah demi mengharap surga atau menjauhi neraka. Tujuan beribadah adalah demi mengharap RIDHO ALLAH Ta'ala. Demi mengharap cintaNya. Bukan begitu?"
***
Sungguh. Aku mendapatkan banyak hal di perjalananku kali ini. Bukan hanya dihujani air dari langit, tapi pikiranku juga dihujani banyak ilmu. Ilmu yang mungkin telah lama kulupakan. Pun ilmu yang belum pernah kudengar.
Bapak itu mengingatkanku, bahwa di dunia ini ada 3 macam jenis manusia. Ada manusia yang hanya mengharapkan surga, ada manusia yang hanya mengharapkan ridho dari Tuhannya, ada pula manusia yang beribadah karena tidak mau masuk neraka. Sedang, sebaik-baik manusia adalah yang beribadah karena mengharap ridho dari Tuhannya. Ia tidak akan peduli dengan surga dan neraka. Sebab baginya, yang terpenting adalah Tuhan bersamanya, dan ia bersama Tuhan.
Itulah yang dinamakan perindu. Perindu yang merindu cinta dari Tuhannya. Bukan surga dan seisinya.
"Kalau begitu, siapakah yang lebih kau rindukan, nak? Ayahmu, atau Tuhanmu?"
Pertanyaan itu begitu tajam. Menampar jiwaku. Membelalakkan mata hatiku. Pertanyaan itu, membuatku harus tertegun beberapa saat sebelum aku berhasil menjawabnya.
"Tentu, setiap hamba pasti merindukan Tuhannya. Tapi tiap kali rindu itu meradang, selalu ada waktu di mana saya bisa bersimpuh, berkomunikasi dengan-Nya. Saya bercengkerama dengan-Nya setiap waktu. Dalam setiap salat dan munajat. Tapi saya juga rindu pada ayah. Dan saya sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengannya. Kecuali hanya dengan mimpi-mimpi yang sesekali, dan doa-doa yang senantiasa. Jadi, menurut saya, rindu pada Tuhan, dan rindu pada manusia itu dua hal yang berbeda. Moga saja, Tuhan selalu menjadi yang terdepan."
"Kau yakin, Tuhan selalu kau nomor-satukan? Bagaimana kalau Tuhanmu cemburu?"
Lagi-lagi pertanyaan itu membelalakkan mata hatiku. Aku terdiam, nyaris bungkam. Hanya memandangi jalanan, mengemudi dengan kecepatan standar. Bagaimana kalau Tuhanmu cemburu?
Pertanyaan itu meraung-raung dipikiranku. Menampar-nampar. Tak mau hilang. Bagaimana bila Tuhanku cemburu? Aku memang sudah lama tak mendapatkan pertanyaan semacam itu. Bahkan mungkin aku hampir lupa. Aku hampir lupa kalau aku kerap kali membuat-Nya cemburu. Dan barangkali, aku pernah terlalu sibuk mencintai manusia, hingga lupa segalanya. Hingga lalai menjalankan perintah-Nya. Aku, ahh aku memang kerap membuat Tuhanku cemburu. Dan sudah lama aku tak menyadarinya.
"Aku.., terlalu sering saya membuat-Nya cemburu, pak. Teramat sering. Lalu apa yang harus saya lakukan? Selama ini saya selalu ingin bertaubat selamanya, tapi nyatanya hanya di bibir saja,"
Apa yang harus saya lakukan? Pertanyaan itu sudah lama meraung-raung dipikiran. Ingin sekali kuluapkan, tapi tak pernah kesampaian. Apa yang harus kulakukan? Itu adalah pertanyaan kenangan. Kenanganku bersama laki-laki terhebatku. Laki-laki biasa yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih berlalu lalang di pikiran, yang belum sempat kuutarakan. Laki-laki yang sering kupanggil "ayah" ini selalu saja tahu apa yang tidak ku mengerti dan apa yang harus ku ketahui.
Ya, dialah penerang sekaligus pengarahku untuk tetap berlari ke tujuan ketika langkahku keliru. Dan kini aku merindukan saat-saat itu. Sudah lama aku tak bertanya, "Apa yang harus ku lakukan?" ketika langkahku keliru dan seruan menuju kebaikan samar-samar ku dengar.
"Ayah, apa yang harus ku lakukan?"
Butiran air hangat berlinang menemani perjalanan yang tak lagi panjang. Berderai, berbaur dengan hujan. Siapapun tak akan tahu bahwa pengemudi sepeda motor berwarna merah ini sedang berurai air mata. Siapapun tak akan pernah tahu, sekalipun para pematuh lalu lintas di lampu merah kota Pecangaan itu.
Biarkan air mataku berurai. Berbaur bersama hujan. Berderai terus berderai. Mengalir, ke ujung kaki, aspal, menggenang bersama hujan, lalu ke sungai, hingga ke lautan.
Karena itulah, Aku suka hujan.
**
"Perbaiki salatmu, nak!" bisiknya perlahan yang segera dicerna oleh pikiran, hati, dan jiwaku.
"Tinggikan kualitas salatmu, nak!" bisiknya lagi yang membuat jemariku gemetar tak mampu mempertahankan laju kecepatan.
"Salatlah seperti ketika kau tahu bahwa esok kau akan mati. Sebab ketika kau menjaganya (salat), maka Ia akan menjagamu,"
*** Dan lagi, beliau membisikiku sesuatu yang bukan sekedar bisikan.
Lagi, setelah ribuan hari lamanya aku merindukan arahan dari lelaki tersayang yang jadi panutan, di perjalanan ini, perjalanan yang penuh dengan air mata rindu, dari langit pun dari mata-hati yang melebur jadi satu, aku kembali mendapat sebuah arahan, pencerahan dari laki-laki biasa yang jiwanya seperti dia; yang sudah tenang di surga Tuhan.
Seorang laki-laki paruh baya, bergamis putih, berkopyah putih, yang tubuhnya tak basah meski kehujanan, yang membuat perjalanan ini begitu hangat meski hujan menghantam habis-habisan, yang menjadikan puluhan kilometer ini terasa begitu dekat dan cepat. Lelaki paruh baya berusia kurang lebih 50 tahun itu. Yang telah mengantarkanku menuju Negeri Cinta, yang di sanalah ayah berada.
***
Kala itu, setelah menempuh 85 kilometer, aku berhenti di tepi jalan. Sebuah jalanan sepi yang tiada siapapun kecuali kami, hujan, dan petir yang menyambar. Beliau turun dan berkata kalau sudah sampai tujuan. Lalu, mempersilakanku melanjutkan perjalanan. Sendirian. Beliau hanya tersenyum, lalu bilang,
"Lain kali jangan pulang malam-malam lagi ya, anak bandel! Lanjutkan perjalananmu! Tak usah khawatir, ayah selalu menjagamu dari kejauhan. Pemberanikan? :)"
"Ayah?"
Aku gusar tak karuan. Air mataku mengucur deras bak banjir bandang. Sesak. Sungguh sesak luar biasa. Pikiranku buyar. Tak tahu arah pulang. Tak mau ditinggal sendirian.
Aku berlari. Meninggalkan sepeda motor yang tak lagi kinclong karena terciprat genangan air hujan. Mengejar laki-laki paruh baya yang tak ku tahui namanya dan ternyata sosok yang ku cinta. Aku berlari. Terus berlari.
"Ayah, tunggu!"
Sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya, aku berlari.
Hingga akhirnya.. Brak!!
Aku berhasil mendobrak gerbang maha luas, tempat ayah berada.
▪Gerbang Utama Negeri Cinta▪▪
***
"Wow, inikah yang namanya Negeri Cinta? Kok panas ya?" (memegang jidat)
"Alamak, nduk," teriak ibu sambil geleng-geleng kepala. "Panas, panas, iya panas! Makanya kalau dibilangin orang tua itu jangan bandel! sudah dibilang jangan pulang malem-malem! Untung semalem pingsannya pas sudah nyampek gang,"
***
Aku suka. Sangat suka. Berkendara sendirian. Kala malam bersama hujan. Asyik, bukan?
Hujan, terimakasih. Kau mengajariku banyak hal.
Jepara, 14 Januari 2017
Diah Fatimatuzzahra
Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
“Artikel ini merupakan kiriman dari pembaca hipwee, isi artikel sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.”






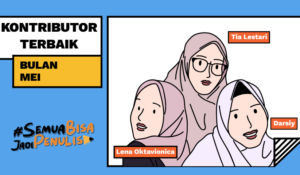








Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.