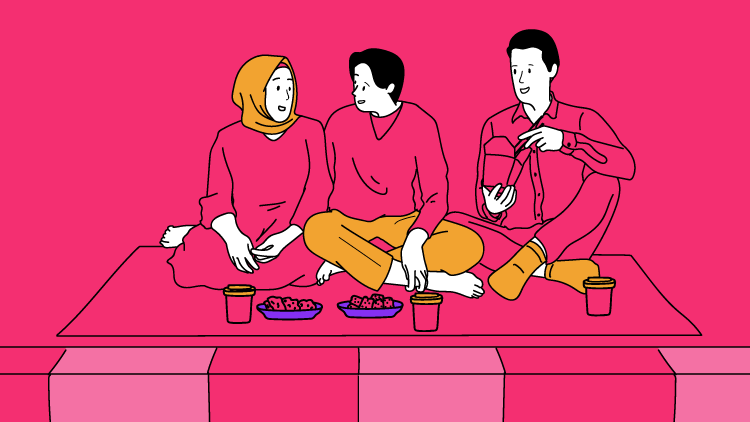Satu tahun setengah kira-kira saya lulus dari sebuah tempat terpencil untuk menuntut ilmu, empat bulan sebelum pandemi kalau mau lebih spesifik. Selama menghabiskan lima tahun jadi anak rantau di sana, rasa-rasanya kok bulan Ramadan jadi salah satu moment yang ternyata meninggalkan kesan yang mendalam ya. Nggak tahu kenapa, setelah mejalani hampir dua bulan Ramadan di rumah, kok rasanya ada yang hilang ya.
Apalagi Ramadan tahun ini dan tahun kemarin rasa-rasanya nggak “ngeunah” karena pandemi yang menerjang dunia. Kita jadi nggak bisa melakukan banyak hal, tentunya hal ini juga memengaruhi saya dan rencana-renca saya. Niatnya di bulan Ramadan tahun kemarin dan tahun ini saya ingin kembali ke tempat terpencil itu buat puasa beberapa hari di sana, for good and old time sake kalau kata orang bule.
Tapi sayangnya rencana itu nggak bisa berjalan, karena ada larangan dari pemerintah yang nggak memperbolehkan masyarakat untuk bepergian. Tapi jujur aja, puasa di tempat rantau, walaupun sederhana terkadang mengena di hati lho. Meskipun terkadang buka puasa di tempat rantau terasa miris dan sedih jika dibandingkan dengan puasa di rumah, toh nyatanya hal itu yang malah bikin saya kangen.
Salah satu moment yang selalu saya ingat adalah sore hari saat mencari takjil untuk berbuka. Karena proporsi tempat berbuka dan jumlah rakyat di sana nggak sebanding, maka setiap berbuka puasa, saya dan kawan-kawan harus berjibaku berebut untuk mendapatkan makanan buka puasa. Percayalah, jika kamu mau enak buka puasa dan bisa menyantap makanan serta minuman secara damai, datanglah jam empat atau setengah lima sore, lebih dari jam itu? Siap-siap saja menelan ludah ketika magrib karena kamu masih menunggu makanan atau minuma kamu diracik oleh penjual.
Rasanya nggak cuma itu aja sih. Buka puasa di daerah kampus karena males balik ke kost sambil ngeceng rasanya juga seru kalau diingat-ingat kembali. Bermodalkan gorengan yang dibeli patungan, es pisang hijau atau es teh manis yang minumnya juga di gilir kadang-kadang, serta rokok yang dibeli secara ketengan, rasanya sudah bahagia sekali saat itu.
Kadang juga saya dan teman-teman kost juga suka bertemu teman-teman sejurusan dan nongkrong bareng, berbagi takjil dan saling meminta rokok satu sama lain, sembari sesekali bertanya jika ada teman lain yang menegur “Boleh tuh, kenalin lah!” Tentunya setelah yang bersangkutan pergi. Bermodalkan uang Rp5000 s.d. Rp10.000 kita bisa senang dan berbahagia, walaupun sedikit amoral kalau dipikir-pikir, pas bulan Ramadan lagi. Gendheng!
Biasanya setelah itu kami akan mencari makanan berat yang tentunya, ramah di kantong mahasiswa ekonomi lemah seperti kami waktu itu, sebelum akhirnya memutuskan untuk nongkrong di tempat kopi, yang tentunya kita sudah kenal dengan penjualnya, jadi nggak malu kalau cuma jajan sedikit tapi nongkrongnya sampai dekat sahur.
Ah iya! Selain berbuka puasa, sahur juga menjadi cobaan dan cerita tersendiri saat itu. Permasalahannya masih mirip dengan buka puasa, tempat sahur yang nggak sebanding dengan rakyat yang ada di sana, makanya jika saya dan kawan-kawan mau sahur dengan pilihan menu yang banyak dan lengkap, kami harus datang ke tempat penjual makanan jam 3 pagi, jika kesiangan, jangan ngedumel kalau kamu hanya akan sahur dengan nasi, sayur bening, dan tempe, jujur saya sih nggak kuat sampai sore kalau menunya begitu.
Delivery nggak pernah jadi pilihan saya dan kawan-kawan kala itu untuk santap sahur. Selain kami kasihan sama mamang-mamang yang nganter, delivery juga nggak efektif. Kalau sedang sial terkadnag makanan yang kamu pesan baru akan datang setelah adzan subuh, tentunya hal tersebut akan menjadi sebuah dilema, kalau makanannya nggak dimakan, akan sayang dan basi, tapi kalau dimakan, ya nggak puasa, silahkan pilih seenak hati aja, hehehe.
Tentunya yang paling asik saat itu menurut saya adalah momen ketika batal puasa. Ketika saya melangkahkan kaki ke dalam rumah makan yang ditutup hordeng/korden, biasanya saya akan segera menyapu seluruh ruangan untuk melihat, adakah muka-muka familiar yang saya kenal dan sedang batal seperti saya saat itu.
Selain itu menolak ajakan batal dari teman selepas ngampus juga menjadi sebuah kegiatan rutin yang saya rindukan. Rasanya jika saya bisa menolak ajakan tersebut dan bisa berpuasa secara full ada kebanggaan tersendiri, selain itu hal tersebut juga terasa menajdi validasi jika diceritakan oleh yang mengajak ke teman-teman lain, saya serasa divalidasi sebagai orang paling alim di tongkrongan, walaupun shalat tarawih masih kabur-kaburan.
Meskipun nggak bisa dipungkiri, berpuasa di rumah terasa lebih hangat dan mudah, apalagi dilakukan dengan keluarga. Puasa di tempat perantauan selalu punya tempat tersendiri di hati saya. Bahkan perasaan saya terenyuh ketika tahu tahun kemarin, lokasi kampus saya sangat sepi karena para mahasiswa harus belajar di rumah karena pandemi.
Nggak ada lagi kerumunan dan mahasiswa yang berjibaku mencari takjil di sore hari atau berkerumun mencari lauk sahur pagi-pagi buta. Semoga, nanti setelah pandemi, semua bisa berjalan normal, mungkin saya akan melakukan hal ini, berpuasa beberapa hari di daerah kampus, meskipun sudah nggak ada teman kost dan rekan sejawat yang sudah mulai lulus satu-satu.