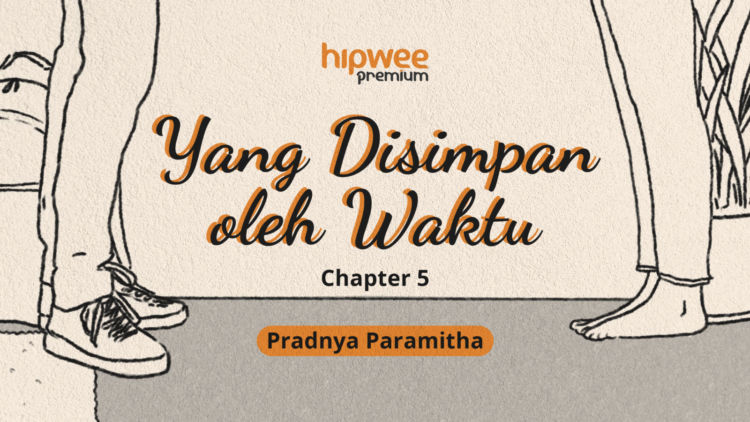Lima belas menit kemudian, bel pintu unit apartemenku berbunyi. Sedikit tertatih, aku membukakan pintu. Wajah Pak Satpam yang pertama kali kulihat.
“Selamat siang, Bu Tara.”
Gegas berdiri di belakangnya, tersenyum tipis ketika aku menatapnya dengan heran. Kupersilakan ia masuk, lalu kuucapkan terima kasih kepada Pak Satpam yang segera kembali untuk bertugas di bawah.
Gegas tengah melihat-lihat foto di dinding ketika aku berbalik dan menutup pintu. Pria itu memakai celana jeans hitam dan kaus lengan panjang biru tua. Seperti biasa, ada ransel di pundaknya dan rambutnya dibiarkan tergerai begitu saja. Ada kantong plastik hitam di tangannya. Ia menoleh dan memandangku dengan ekspresi menelaah yang familier itu.
“Lo oke?” tanyanya.
“Nggak,” jawabku jujur, sembari mengempaskan diri ke sofa ruang tamu. “Sama sekali nggak oke.”
Memangnya ada yang akan percaya kalau aku bilang baik-baik saja, saat penampilanku saja sudah seperti keset rumah?
“Ngapain ke sini?” tanyaku. “Gue pikir lo udah balik ke Wamena atau udah entah ke mana.”
Sebenarnya agak aneh bagaimana Gegas ada di sini. Gegas, mantan sahabatku yang bahkan tidak mau memberiku nomor teleponnya. Sayangnya, kini aku paham alasan di balik itu semua.
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

“Gue pengin tahu sebesar apa kekacauan yang gue buat.”
Sontak aku tertawa mendengar jawaban Gegas. Entah tawa macam apa yang kulakukan sekarang, tetapi rasanya berbeda dengan tawa-tawa yang kubuat belakangan. Sudah lama sekali aku tidak mengeluarkan tawa sejenis ini.
“Sebesar ini, berengsek!” jawabku sembari mengibaskan tangan, menunjukkan apartemenku yang berantakan dan berbau seperti muntahan. “Egi sialaaan!” desisku sembari menyandarkan kepalaku ke punggung sofa dan memejamkan mata.
“Di mana dapur?” Gegas bertanya.
Lagi-lagi aku melambaikan tangan secara sembarangan, tanpa repot-repot membuka mata. Entah mau apa Gegas di dapurku, mungkin dia sedang menyindir karena aku tak menawarinya minuman. Biar sajalah.

Illustration by Hipwee
Gegas berkutat di dapur apartemenku cukup lama. Lalu, dia kembali membawa nampan dengan mangkuk dan segelas air putih. Aroma gurih menguar ke mana-mana. Aku membuka mata sedikit dan menatapnya dengan penasaran.
“Gue beli bubur di bawah tadi. Asam lambung lo pasti kambuh,” katanya, sembari menaruh nampan itu di meja tepat di depanku.
Aku berdecih. “Nggak mati aja udah hebat.”
“Sstt! Nggak usah omong sembarangan. Makan buruan!”
Bahkan, tanpa menatap wujudnya pun, aku tidak berselera.
“Lo mau apa ke sini?” tanyaku sekali lagi, masih dengan kepala menyandar di punggung sofa dan mata terpejam.
“Gue mau minta imbalan yang lo janjikan.”
Sontak aku membuka mata. Ah, benar juga. Kok aku bisa lupa? Gegas bilang informasi darinya tidak gratis dan aku menyetujuinya.
“Oh, iya.” Aku mengangguk. “Apa imbalan yang lo minta? Ganti biaya tiket pulang-pergi ke Wamena?” tanyaku.
Gegas menggeleng.
“Biaya layanan informasi? That’s ok. Sebut aja berapa, nanti gue transfer.”
Gegas masih menggeleng.
“Terus? Ah … apa mungkin dulu lo sama Egi bertengkar karena sesuatu yang berbau materi? Ada sesuatu yang bisa gue ganti rugi?”
Aneh, Gegas masih saja menggeleng.
“Jadi, imbalan apa yang lo mau?” tanyaku mulai tidak sabar.
“Gue mau lo dengerin gue sekarang, dan turutin semua permintaan gue.”
Sebelah alisku mencuat. Satu kecurigaan muncul, memantik rasa tersinggung dan terhina yang lebih dalam.
“Ingat, lo janji bakal nurutin apa pun imbalan yang gue minta, kan?”
Setitik ketakutan mulai mencekam tengkukku. Ini Gegas, kan? Gegas tidak mungkin meminta yang aneh-aneh, kan?
“Gue mau lo—”
“Jangan macam-macam lo, Gas—”
“—memaafkan Egi.”
“Hah?”
Gegas mengangguk. “Gue yakin lo butuh waktu buat mencerna semua ini. That’s ok. Take your time. Mungkin lo benci Egi sekarang setelah lo tahu yang sebenarnya. Mungkin lo berharap Egi hidup lagi supaya lo bisa maki-maki dia secara langsung.”
Aku mengangguk. Tepat itulah yang kuinginkan. Lebih dari itu, aku ingin Egi hidup lagi agar aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri.
“Tapi yang udah terjadi nggak bisa dibalikin kan?” Gegas bertanya. “Seruni dan Egi adalah masa lalu. Ini bukan kisah yang bagus, tapi gue harap lo bisa maafin Egi atas semuanya.”
Aku mendengkus sinis. “Gampang amat lo ngomong gitu. Lo nggak tahu apa yang gue rasain.”
“Memang nggak tahu,” jawab Gegas cepat.
“Gue sama Egi udah 4 tahun, Gas! Kalau aja Egi nggak mati, gue bakal nikah sama dia! Bisa-bisanya dia sembunyiin hal kayak gini dari gue! Lo tahu, kan? Lo tahu gimana gue koar-koar membenci perselingkuhan? Gimana ceritanya si berengsek itu malah jadiin gue selingkuhan?!”
Kekesalan yang kupendam kembali meledak. Inilah yang kubutuhkan selama beberapa hari terakhir. Bukan kata-kata penyemangat, bukan kata-kata hiburan, melainkan kesempatan untuk mencaci maki keadaan. Mencaci maki Egi tanpa perlu dihakimi sebagai tunangan yang tidak tahu diri.
“Ngerti, Ra, ngerti. Lo adalah orang yang paling berhak untuk marah di sini. Gue nggak melarang. Marah aja, nggak apa-apa. Tapi, gue berharap lo ingat satu hal. Kemarahan nggak mengubah apa pun.” Gegas menatapku. “Termasuk gimana sikap Egi selama ini ke lo.”
Aku menatap Gegas, tidak mengerti dengan kalimat terakhir yang ia ucapkan.
“Coba singkirkan dulu fakta tentang Seruni. Lalu, ingat lagi gimana sosok Egi yang lo kenal selama ini. Seperti apa sikapnya, apa aja yang kalian lakukan bareng, apa aja yang dia lakukan buat lo.” Gegas menyatukan kedua tangannya di bawah dagu. “Gue tahu kalau sikap Egi sama lo dan Seruni itu salah. Itu bukan hal yang bisa gue toleransi juga. Tapi, jangan sampai karena kesalahan itu, lo menghapus semua nilai positif dari Egi, Ra.”
Aku mengerti. Aku memahami maksud Gegas. Namun, tetap saja ini bukan hal yang mudah.
Aku mendesah, mendadak begitu lelah. “Masalahnya, gue nggak tahu apakah Egi beneran pernah cinta sama gue, Gas. Surat itu terakhir ditulis bulan Februari tahun ini. Sebulan sebelum pernikahan kami. Itu artinya, sampai akhir, Egi masih mikirin Seruni. Lalu …” Aku menggigit bibir. “Tempat gue di mana?”
Gegas memajukan tubuhnya, lalu menepuk tanganku dua kali. “Di hati Egi. Beneran. Dia cinta sama lo kok, Ra.”
Kutepis tangan Gegas. “Jangan sok tahu! Lo ngilang bertahun-tahun, lo nggak tahu apa-apa soal gue sama Egi!”
“Tahu,” jawab Gegas cepat. “Dari Egi. Dia bilang sendiri.”
Aku memasang ekspresi menuntut, ingin Gegas menjelaskan lebih banyak lagi. Kapan mereka bertemu? Bukankah selama ini Egi bahkan menetapkan kata “Gegas” sebagai kata yang terlarang dan sebagai dia-yang-namanya-tak-boleh-disebutkan?
“Egi itu cuma manusia yang sedang sial karena mencintai dua orang dengan porsi yang sama. Yang kayak gitu … manusiawi aja, kan? Soal perasaan kadang nggak bisa kita kendalikan. Lagian, pada akhirnya, Egi tetap milih juga kan? Meski dia masih belum lupain Seruni sepenuhnya, dia memutuskan untuk membuat komitmen sama lo.”
Aku terdiam. Kata-kata Gegas membuatku teringat sesuatu. Terburu-buru, aku bangkit dari tempat duduk dan masuk kamar. Kuambil surat-surat Egi yang diam-diam kubawa pulang ke apartemen. Sekali lagi, kubaca surat terakhir yang tertanggal 18/02/2018 khususnya di paragraf terakhir.
Ini akan menjadi surat terakhir yang kutulis. Bulan tiga tanggal 18 nanti, aku dan Tara akan menikah. Aku akan belajar menerima bahwa ini adalah perpisahan kita yang sebenarnya.
“Lo tidur? Gue belum selesai!” terdengar teriakan Gegas dari luar ruangan.
Kuabaikan teriakan itu karena pikiranku terlalu riuh. Benarkah apa yang dikatakan Gegas tadi? Kalimat ini … apakah ini artinya Egi berniat melepaskan Seruni sepenuhnya dan memulai lembaran yang benar-benar baru denganku? Apakah pada akhirnya Egi bertekad melupakan perempuan itu? Apakah jika kami menikah, Egi tidak akan menulis surat untuk Seruni lagi?
“Kenapa gue mau lo memaafkan Egi, itu karena lo juga harus maafin diri lo sendiri, Ra.” Di luar kamar, Gegas masih terus berusaha. “Lo nggak salah apa-apa, tapi gue yakin sekarang lo merasa bersalah. Lo merasa jadi sosok perebut pacar orang lain. Gue mau lo maafin Egi, karena hanya dengan itu lo bisa maafin diri lo sendiri.”
Aku masih tidak menjawab. Kuhela napas panjang dan mendongak. Mataku langsung menemukan sebuah poster superbesar yang kutaruh di atas meja kerja. Poster itu berukuran 2×1 meter. Itu bukan poster artis idola, melainkan berisi rute transportasi umum di Jakarta. Egi yang membuatkannya di tahun 2014 lalu, saat aku baru saja kembali ke Jakarta dan sering bingung menggunakan transportasi umum. Egi membuatkanku tiga alternatif rute dan moda transportasi untuk tempat-tempat yang sering kukunjungi.
Rute pertama adalah dengan TransJakarta. Ia menandai nomor-nomor bus yang bisa kutumpangi, koridor mana yang harus kugunakan, dan halte apa saja yang mungkin akan kulalui. Lalu, rute kedua adalah dengan moda transportasi KRL. Egi bahkan mencantumkan beberapa pilihan jadwal KRL yang bisa kupakai serta estimasi waktu aku akan tiba di kantor. Rute ketiga, tertulis di bagian paling bawah dengan font yang paling besar. Egi mencantumkan nomor teleponnya dengan keterangan “Rute paling cepat, praktis, antinyasar. Siap mengantar ke mana pun Anda bepergian.”
Aku tersenyum tipis. Mengingat pada akhirnya rute terakhirlah yang paling sering kugunakan.
“Sekarang gue akan sampai di bagian saran-saran klise yang mungkin udah lo dapatkan dari ribuan orang sebelumnya. Egi udah pergi, tapi lo masih di sini, Tara.”
Ya, tentu saja. Egi sudah pergi, tetapi aku masih di sini. Hidup sudah cukup melelahkan tanpa harus diisi dengan kebencian dan kemarahan.
“Hidup lo terus berjalan, pilihannya hanya satu: Lo harus bahagia. Nggak harus sekarang, tapi lo harus move on. Lo harus melanjutkan hidup dan untuk itu, lo harus maafin diri lo sendiri dulu, kan?”
Sekali lagi kuhela napas panjang dan kusimpan kembali surat-surat itu di dalam laci. Kuambil sisir di meja rias, dan sebisanya kurapikan rambutku yang seperti sarang burung. Kuikat rambutku dengan ekor kuda, dan kubasuh wajahku di wastafel kamar mandi.
Aneh. Belakangan kupikir kulitku mati rasa, tetapi hari ini air terasa segar juga. Entah Mylanta berhasil menjinakkan lambungku atau sugesti dalam pikiranku yang bekerja, kini aku merasa lebih baik.
Gegas masih duduk di tempat yang sama saat aku keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang lebih layak. Ugh! Ekspresi itu! Sampai kapan Gegas akan mempertahankan ekspresi menelaah yang menyebalkan itu?
“Benci, marah, kecewa itu boleh aja. Tapi jangan lama-lama—”
“Iya, iya!” potongku. “Bawel banget, sih? Sejak kapan lo berubah karakter jadi banyak omong begini?”
Aku duduk kembali di tempat yang tadi kutinggalkan. Kuraih mangkuk bubur dari Gegas yang sudah dingin. Kuaduk perlahan, lalu kumakan pelan-pelan.
“Lo benar, Gas,” kataku di sela-sela makan. “Sebenci apa pun gue sama Egi, dia mungkin orang yang paling banyak berkorban dan ngasih gue pemakluman.”
Kini giliran Gegas yang memandangku dengan ekspresi bingung.
“Lagian gue mau marah lama-lama juga percuma. Egi nggak bisa berlutut di depan gue buat minta maaf, kan?”
“Ra?”
“Terus kesehatan gue juga jadi berantakan. Kerjaan gue numpuk karena terbengkalai.” Kutelan sesuap bubur. “Percuma banget. Mungkin ini bisa jadi pelajaran. Next time gue perlu melakukan background checking lebih teliti sebelum nembak cowok, buat mastiin dia benar-benar nggak ada gandengan.”
Awalnya, Gegas masih memberiku tatapan bingung yang berubah dengan tatapan menganalisisnya yang biasa. Namun, karena aku tetap makan dengan lempeng, menelan sesuap demi sesuap bubur hingga tandas, akhirnya Gegas tersenyum.
“Good. Itu baru Tara yang gue kenal.”
Aku mengedikkan bahu. “Sisi baiknya, kejadian ini bikin kita bisa reunian, ya? Lo ke mana aja sih, Gas? Macam intel aja, jejak lo nggak kebaca. Terakhir ketemu pas di Soetta dulu, kan? Itu juga nggak sempat ngobrol.”
Gegas tertawa lagi. Lantas ia pun bercerita bahwa dia terburu-buru saat itu karena harus mengejar check in pesawat yang akan membawanya ke Lombok. Dari sana, obrolan berkembang ke apa saja yang Gegas lakukan selama tiga tahun ini. Ternyata Gegas sudah tinggal di Wamena selama setengah tahun belakangan. Ia dan komunitasnya tengah membantu pengembangan potensi masyarakat lokal. Dari kisah hidup Gegas, obrolan berpindah ke kisah hidupku sendiri. Sayangnya, dibandingkan hidup Gegas, hidupku terasa membosankan dan tak seru.
“Jadi, setelah ini lo bakalan balik ke Wamena?” tanyaku.
Gegas mengangguk. “Tapi cuma sebentar sih, program yang di sana udah hampir beres.”
“Terus habis itu?”
Ia mengedikkan bahu. “Entah. Mungkin ke Aceh atau Kalimantan. Gue belum pernah ke sana. Siapa tahu jodoh gue ada di sana, kan?”
Jawaban Gegas berhasil membuatku tertawa lepas. Ah, ini rasanya seperti momen-momen lawas kami. Waktu di mana kami bertiga sering nongkrong hingga dini hari. Ngobrol ngalor-ngidul, dari yang berfaedah hingga sampah. Sejak dulu, kebebasan Gegas selalu membuatku iri. Gegas tidak pernah menambatkan kakinya di satu tempat untuk bisa makan. Beda denganku yang terpatok jam kerja nine to five setiap harinya untuk bisa melunasi segala tagihan yang datang setiap bulan.
“Atau mungkin sebenarnya jodoh lo itu di sini-sini aja, Gas. Lo-nya aja yang main mulu, makanya nggak ketemu,” selorohku.
“Gitu, ya?” Gegas meringis kecut. Hey, selain jadi lebih banyak omong, Gegas yang ini juga lebih banyak berekspresi.
“Iya. Kayak … apa itu yang kata pepatah? Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian?”
“Ngawur!” Gegas tertawa.
Lima belas menit kemudian, Gegas pamit untuk pulang. Ia juga berpesan agar daripada hanya makan sereal, sebaiknya aku pesan-antar makanan dan minta tolong Pak Satpam untuk mengantarkannya ke atas jika aku tidak sanggup turun ke bawah. Entah dari mana dia tahu aku hanya makan sereal empat hari belakangan. Mungkin diam-diam dia menginspeksi isi kulkasku saat aku di kamar.

Illustration by Hipwee
“Gas,” panggilku saat Gegas tengah memakai sepatu kets-nya.
“Hmm?”
“Gue boleh tahu apa yang terjadi antara lo sama Egi?” tanyaku sedikit ragu.
Sontak Gegas mendongak untuk menatapku. Kali ini ekspresinya tidak terbaca.
“Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi mewakili Egi, kalau memang dia ada salah sama lo, gue minta maaf, ya?”
Gegas menggeleng. “Nggak kok, Ra. Nggak ada yang perlu minta maaf atau dimaafkan. Gue juga salah. Intinya gue sama Egi nggak sepaham aja. Egi melakukan kesalahan, tapi gue juga bertindak melampaui batas.”
“Apa ini juga soal Seruni?” tanyaku.
“Salah satunya.”
Kuhela napas panjang. “Iya, sih. Lo pasti marah banget karena sepupu lo diperlakukan kayak gitu. Kalau gue jadi lo, gue juga pasti nggak mau kenal Egi lagi.”
Setelah memastikan tali sepatunya terpasang dengan benar, Gegas berdiri dan menatapku. “Salah satunya itu. Salah duanya, gue juga nggak rela lo diperlakukan kayak gitu.”
“Gue?” Aku mengangkat alis. “Kenapa?”
“Gue nggak rela Egi menjadikan lo opsi kedua …” Gegas tersenyum. “Karena lo selalu jadi opsi pertama buat gue, Ra.”
TAMAT