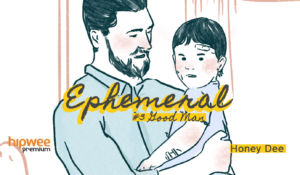Waktu itu akhir pekan dan Jakarta diguyur hujan. Aku dan Candra berniat pergi ke PIK untuk mencicipi es krim dari kedai yang kulihat fotonya via Instagram. Mungkin baru satu bulan berselang dari pertemuan pertama, tapi kami sangat akrab. Hari itu, karena aku tidak mau terjebak macet atau kemungkinan banjir akibat hujan deras, akhirnya kami memutuskan untuk memasak di apartemen Candra.
Aku masih ingat, di tengah proses aku memotong cabai dan Candra membersihkan ikan, dia berkata, “I want to be your boyfriend.”
Hampir saja jariku teriris pisau. Kalimatnya seperti petir menyambar karena sebelumnya kami tengah mentertawakan eksperimen kue sus yang gagal. Bagaimana bisa pembicaraan itu berujung pada keinginannya untuk mengganti status sebagai pacar?
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

“Why?” tanyaku.
Tanpa menghentikan kesibukannya, Candra menoleh ke arahku. “Because I like being with you.”
Ketulusannya tidak terbantah hingga puncaknya, senyum Candra yang kusukai muncul di permukaan. Perlawananku tinggal sejarah, bukan berarti aku hendak menolak. Aku juga suka menghabiskan waktu bersamanya. Candra membuatku tertawa, bahkan ketika dia tidak banyak berkelakar. Juga membuat jantungku berdebar, meski tidak ada kalimat manis yang berhasil dia rangkai.
Kini, berdiri di apartemennya dengan kardus kosong yang siap diisi barang-barang, aku merasa tidak sanggup melakukannya. Namun, itulah alasanku datang. Mengambil barangku yang tertinggal di apartemen Candra.
“Kira?”
Panggilannya menyentakku. Aku harus melancarkan rencana berikutnya: mengajak Candra mengobrol. Usahakan dalam suasana santai. Maka aku bertanya, “Kamu … um, ada acara nggak setelah ini? Kalau nggak ada, mau lunch bareng? Aku lapar.”
Candra melirik jam dinding yang baru menunjuk angka sebelas. Jika bingung terhadap ajakanku, dia tidak menunjukkannya. Sejak dulu, dia memang paling tidak bisa membiarkanku kelaparan. “Mau makan apa? Aku belum sempat belanja, kayaknya cuma ada telur di kulkas.”
“Apa aja, kamu tahu aku suka apa pun yang kamu masak,” jawabku. Bukan sekadar lip service, sebab kemampuan memasak Candra jauh lebih baik dibanding aku. Dia bisa membuat menu sederhana menjadi istimewa karena rasanya yang lezat.
Sepuluh menit kemudian, tumis tomat telur tersaji di meja makan kecil apartemen Candra. Dia tahu ukuran nasi yang kumakan, jadi kami bersiap tanpa kata. Rasanya aku bisa menangis detik ini juga karena begitu merindukannya. Kegiatan sederhana yang hangat ini kusia-siakan karena salah paham. Sekali lagi, Winny benar, aku memang bebal.

Makan siang yang canggung | ilustrasi: hipwee via www.hipwee.com
“How are you?” Pertanyaan basa-basi itu kumaksudkan untuk mencairkan suasana, tapi lambatnya respons Candra membuat kecanggungan merebak. Setelah dia berkata semua baik-baik saja dan balik menanyakan kabarku—yang kujawab, sibuk bekerja seperti biasa—keheningan panjang menyapa.
Baru kusadari, selama satu tahun menjalin hubungan, Candra sudah berusaha lebih banyak melisankan kata. Kini, kami kembali menjadi orang asing. Tidak heran Candra setia pada diam.
Selesai makan, Candra tidak membiarkanku membantunya mencuci piring dengan alasan aku harus segera membenahi barang. Mungkin itu caranya mengusirku secara halus. Rencanaku jelas lebur, tapi selama menyusun tumpukan kartu UNO, aku sampai pada kesimpulan bahwa aku harus menjelaskan segalanya. Terlepas dari hasil akhirnya, aku hanya ingin jujur kepada Candra. Aku sudah bersikap tidak adil dengan menimpakan segala kesalahan padanya, padahal jika ada yang harus disalahkan, akulah orangnya. Masalah kami tidak perlu menjadi besar kalau saja aku berkomunikasi dengan benar. Kalau saja aku sadar sudut pandangku kurang luas.
Aku berpikir cinta itu harus diucapkan, sama sekali tidak mau melihat cinta Candra bentuknya berbeda.
“Kartunya ada yang hilang?” tanya Candra sambil menghampiriku yang berdiri diam di tengah apartemen. “Terakhir kita main UNO ….”
Dia tidak perlu menyelesaikan kalimat itu, sebab masih segar di ingatanku bagaimana malam itu berlangsung. Aku yang sangat kompetitif gemas karena kalah terus-menerus. Seperti bocah tantrum, aku melempar kartu UNO ke sembarang arah, lalu menyerang Candra. Dia terbahak sementara aku menggelitiknya. Kami berakhir di lantai dengan napas terengah, mata bertatapan dalam, lalu ….
“Kira?”
Aku tersentak. “Ya?”
“Kamu nggak apa-apa?” tanyanya. Mungkin cemas karena hampir satu jam berada di sini, tingkahku tidak karuan.

Kartu UNO penuh kenangan | Ilustrasi: hipwee via www.hipwee.com
Aku terlalu mencemaskan apa yang harus kukatakan dan bagaimana reaksinya. Padahal waktuku terbatas. Maka tanpa menahan diri, kubiarkan rangkaian kalimat meluncur dari bibirku.
“Hubungan kita jadi berantakan karena aku berpikiran sempit. Aku pikir, cuma aku yang cinta kamu. Aku pikir … kamu nggak cinta aku.”
Candra tampak terkejut. “Kenapa kamu mikir gitu?”
Tawa singkatku terdengar menyedihkan, tapi pilihannya hanya itu atau menangis sesenggukan. “Karena kamu … nggak pernah bilang cinta sama aku.”
Kujelaskan betapa absennya kata cinta darinya mengganggu, hingga pikiran-pikiran burukku sehubungan dengan hobinya mengantar-jemput. Selama aku bicara, Candra menatapku tanpa jeda. Lagi-lagi, ekspresinya tidak bisa kubaca. Namun, kini, aku memahaminya. Itu adalah cara Candra memproses. Dia memang kurang ekspresif, tapi perasaannya tidak pernah main-main. Sesuatu yang seharusnya aku apresiasi, alih-alih mendasari perpisahan kami.
“Aku minta maaf, Candra ….” ujarku dengan suara bergetar. Buru-buru aku berdeham untuk menghilangkannya. “Aku egois. Bukan aku yang berhak untuk dapat seseorang lebih baik, tapi kamu. You deserve so much better than me. And I sincerely hope you’ll find her.”
Hening.
Candra meraih tumpukan kartu di tanganku, lalu meletakkannya di kardus. Jemarinya menyusup ke sela-sela jariku, menggenggam erat. Bisa kudengar helaan napas panjangnya, disusul suara beratnya yang berkata, “I found you, Kira. I don’t need someone better.”
Mata kami saling memandang, membiarkan beberapa detik dilalui senyap.
“Harusnya aku berjuang lebih keras,” lanjutnya. “Harusnya waktu kamu bilang putus, aku nggak langsung nyerah.”
Aku menggeleng. “Aku yang salah. Bukan kamu, Candra.”
“Kita sama-sama salah,” koreksinya. “Waktu kamu bilang sesak dan nggak bahagia sama aku, tanpa sadar aku ingat … hubunganku sebelumnya. Itu yang bikin aku langsung nyerah.”
Mataku mengerjap. Ini salah satu pembahasan yang selalu Candra hindari: mantan. Aku hanya tahu dia pernah sekali menjalin hubungan cukup serius sebelum bersamaku. Namun, bibirnya terkatup untuk pertanyaan apa pun berkenaan perempuan itu. Aku sempat berprasangka Candra masih mencintai mantannya, mungkin karena itu dia tidak bisa mencintaiku.
“What happened?” tanyaku.
Candra memejam sesaat, lalu menatapku dengan luka yang tidak disembunyikan. “Aku nggak sengaja dengar… dia bilang aku membosankan. Satu-satunya alasan dia bertahan sama aku karena mukaku nggak malu-maluin diajak kondangan. Dia nggak bahagia dan aku jadi tali kekang yang nahan kebahagiaannya. Aku nggak mau jadi penyebab kamu merasa begitu juga, Ra.”
Kugigit bibir kuat-kuat. Sama sekali tidak menyangka itu alasannya.
“Maaf ….” bisikku. “Aku nggak tahu.”
Candra menggeleng. “Harusnya aku bilang ke kamu dari dulu …. Aku sayang kamu, Kira.”
Pandanganku mulai kabur, maka kukerjapkan mata dan Candra menangkap tetes-tetes air itu. Dia mendongakkan wajahku, lalu menunduk.
Tepat di atas bibirku, dia berbisik, “I’m in love with you.”
***
“Lipstikku aman, kan?” tanyaku. “Rambut masih rapi?”
Candra tertawa pelan, lalu menghentikan tanganku yang sibuk menyisir rambut sebahu. Memang kemungkinan rambutku berantakan selama naik mobil sangat kecil, tapi aku tidak mau tampil kurang dari sempurna di depan keluarga Candra.
Setelah pembicaraan di apartemennya, kami sepakat untuk kembali bersama, tapi menjalaninya perlahan. Komunikasi kami jelas-jelas perlu perbaikan. Aku dan Candra tahu ada banyak hal yang harus kami benahi sekaligus hadapi, tapi semua akan kami lakukan sebagai tim. Tidak ada lagi asumsi yang dibiarkan tumbuh liar hingga menjadi jurang pemisah. Karena itu, perkenalan dengan orangtua Candra baru terealisasi tiga bulan setelah hari bersejarah tersebut.
“They’ll love you,” ucap Candra sambil menarikku menuju pintu. Rumah bernuansa putih yang menjadi tempat tinggal orangtuanya tergolong mewah dan mengintimidasiku, tapi terlambat untuk mundur. Kami sudah berjalan terlalu jauh. “Kamu tahu kenapa? Karena kamu cerewet. Itu alasan Dhirra jadi anak kesayangan Mami dan Papi.”
Aku mencebikkan bibir. “Kirain karena aku baik, cantik, pintar, dan punya kerjaan tetap.”
Candra kembali tergelak. “Itu juga, tapi yang jelas, aku bahagia sama kamu. Keluargaku pasti bisa lihat dan mustahil mereka nggak ikut jatuh cinta setelah tahu itu.”
Ucapan Candra menjadi nyata karena hanya dibutuhkan beberapa menit untuk membuatku akrab dengan keluarganya. Papi Candra mungkin sedikit kaku, tapi maminya memiliki kepribadian secerah matahari yang membuat siapa pun tak kuasa menahan senyum. Tambahkan Bara yang suka melempar lelucon dan Dhirra yang ramai, makan malam itu berlangsung hangat.
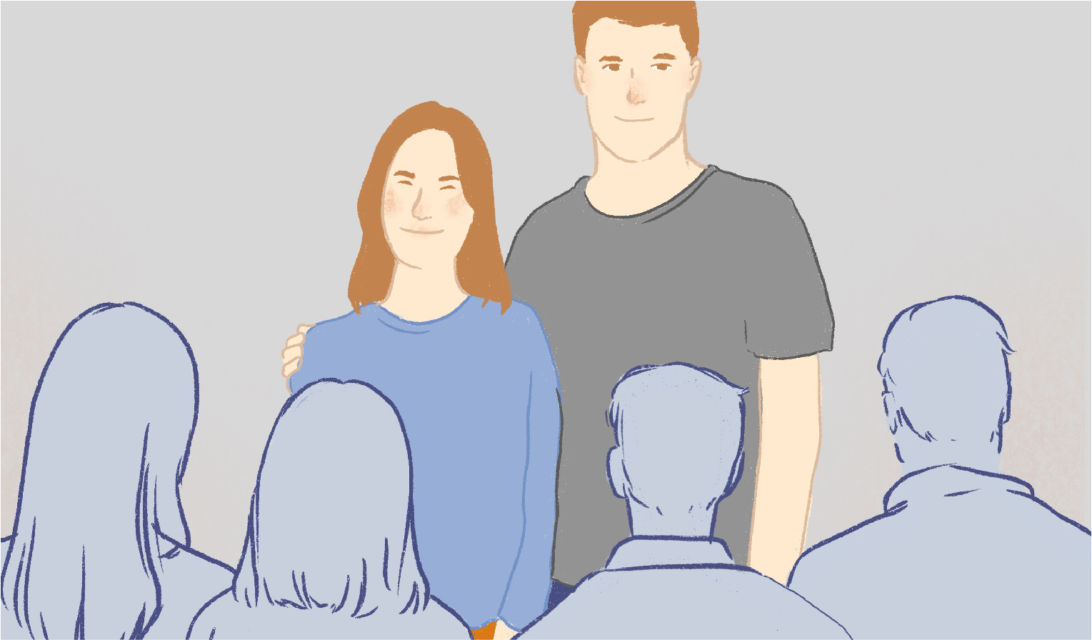
Akhirnya Kira bertemu keluarga Candra | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
“Mi, jangan lupa bilang makasih sama Kira,” ujar Dhirra.
“Oh, iya!” Mami Candra menepuk tangannya, lalu tertawa. “Kira, makasih ya sudah bikin anak saya jadi rajin cukuran.”
Aku yakin, ekspresiku tampak bodoh sekarang. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang mereka bicarakan.
Dhirra menolong dengan menjelaskan, “Sebelum jadian sama lo, Candra tuh suka jadi manusia gua saking sibuk kerja. Awalnya gue sama Mami bingung, kenapa Candra setahun terakhir rajin cukur? Dia bilang, karena lo nggak suka mukanya penuh rambut. Canggih banget sih lo, Ra, berhasil mengasah bakat bucin abang gue di jalan yang benar.”
Mataku menatap Candra tidak percaya. “Kapan aku bilang nggak suka?”
“Waktu kita jalan sebulan. Kamu ke apartemenku dan kita nonton Wreck-It Ralph, terus kamu ci—”
“Okay!” Aku membekap mulut Candra, kini ingat dengan jelas apa yang kulakukan saat memprotes soal rambut di wajahnya. Pipiku terasa memanas, apalagi saat kulihat Bara dan Dhirra menahan tawa. “But you don’t have to do it for me. Kalau kamu suka punya janggut dan teman-temannya, aku nggak akan maksa kamu buat cukur.”
Candra tidak membalas, tapi senyum yang menjadi kesukaanku itu terulas. Meski tanpa kata, aku mengerti dia tidak keberatan. Dia melakukannya dengan senang hati, asal aku bahagia. Begitulah cara Candra mengungkapkan cinta.
Dan, aku tidak akan pernah meragukannya lagi.
-TAMAT-

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
I’m an author of 21 novels under the pen name Nureesh Vhalega. Besides writing, I’m a member of the bookstagram community with account @nuifebrianti.