Selama ini Muara hanya tahu kisah cinta Joval dan Amini dari gosip-gosip di kantor. Namun, setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi dari bibir Joval sediri, masihkah Muara berniat melanjutkann misinya?
***
“Pak, maaf. Boleh saya izin pulang? Om saya meninggal.” Detak jantung Muara nyaris berhenti saat mengetahui kabar mengejutkan.
Joval mendapati raut wajah sedih diikuti bulir bening yang menumpuk di pelupuk mata Muara. Selama mengenal Muara, dia baru sekali melihat pegawainya itu menangis–saat gagal mendapatkan hak asuh untuk klien mereka. Sisanya dia melihat senyum cerah dan keceriaan Muara. Kali ini dia melihatnya lagi–bisa dibilang lebih hancur.
“Boleh, Pak? Seandainya gaji saya dipotong juga nggak apa-apa. Saya pengin lihat Om saya, Pak,” mohon Muara. Air matanya tertahan.
“Boleh. Saya antar kamu ke rumah sakit.”
“Nggak usah, Pak. Biar saya naik taksi aja,” tolak Muara.
“Nggak apa-apa. Saya perwakilan kantor.”
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

Muara sudah tidak bisa menolak atau memaksa agar dibiarkan pulang sendiri. Pikirannya berkecamuk dalam kesedihan yang luar biasa. Om yang selama ini dia sayangi telah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Karena perasaan sedihnya, dia sampai linglung dan nyaris terbentur pintu karena lupa membuka pintu. Untung saja sebelum kepala menghantam pintu, dia sudah lebih dulu menahan diri dan segera membuka pintu.
Joval yang memperhatikan Muara menjadi sangat khawatir. Kabar duka itu tampaknya mempengaruhi fokus Muara. Dia bergegas keluar membawa sejumlah barang penting sebelum mengantar Muara melihat omnya.
***
Setengah jam perjalanan akhirnya Muara tiba di rumah duka. Sanak keluarga berdatangan, karangan bunga berjejeran rapi mengisi depan ruangan. Muara memeluk keluarga yang lain dan menangis dalam pelukan satu per satu orang yang dia kenal, terutama anak-anak dari omnya. Dalam sekejap Muara melupakan Joval yang sudah menemaninya, berfokus pada keluarganya saja selama beberapa waktu ke depan.
Selagi Muara menyapa keluarga, Joval berdiri di depan. Dia tidak enak masuk ke dalam karena Muara tidak di sampingnya. Dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan orang tersayang. Tantenya dari pihak ibu sangat akrab dengannya dan ketika meninggal, Joval sangat kehilangan.

Muara dan keluarga diselimuti duka | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
“Pak Joval.”
Joval menoleh ke belakang—menemukan Muara. Mata gadis itu merah dan berair. Tampaknya belum selesai menangisi kepergian omnya. “Ya, Muara?”
“Maaf saya melupakan, Bapak. Ayo, masuk, Pak. Biar saya kenalkan sama keluarga om saya,” ajak Muara. “Setelah masuk Pak Joval ingin pulang, nggak apa-apa. Saya nggak mau Pak Joval berlama-lama di sini, takut ada urusan yang penting di kantor.”
“Nggak apa-apa, kok. Kamu tenang aja. Saya temani kamu di sini.”
“Kita masuk dulu, Pak.”
Muara mengajak Joval masuk ke dalam, memperkenalkan pada satu per satu keluarga Handoyo yang datang termasuk hampir seluruh sepupunya. Keluarganya termasuk keluarga besar dan semoga saja Joval tidak mendadak pusing karena banyaknya nama yang disebutkan. Setelah mengajak berkenalan, dia membawa Joval sampai ke depan peti. Dia tidak bisa menahan tangisnya.
“Om, ini yang namanya Pak Joval, bosnya Muara,” ucapnya lirih.
Joval tidak tahu harus merespons bagaimana. Dia cuma bisa menepuk pundak Muara saat perempuan itu akhirnya menangis terisak-isak di depan peti. Selama beberapa menit dia mendengar Muara menangisi omnya. Hingga akhirnya dia berlalu mengikuti Muara.
Di depan rumah duka terdapat beberapa bangku. Joval duduk bersampingan dengan Muara. Perempuan itu masih sedih bahkan isak tangisnya samar-samar dapat ditangkap telinga. Joval menyodorkan sapu tangannya kepada Muara agar tidak perlu menyeka dengan tangan.
“Nggak usah, Pak, nanti sapu tangannya kotor,” tolak Muara seraya mendorong tangan Joval untuk mengambil kembali sapu tangan tersebut.
“Nggak apa-apa. Lebih kotor kalau tangan kamu kena muka. Sapu tangan saya baru, kok, belum dipakai seharian ini.” Joval kembali menyodorkan sapu tangannya, yang mana akhirnya diambil oleh Muara. “Kamu paling dekat sama om kamu itu, ya?”
Sambil menyeka air mata dengan sapu tangan, Muara menjawab, “Iya, Pak. Waktu SMA kelas satu, orangtua saya meninggal kecelakaan pesawat. Saya anak tunggal. Om saya yang merawat dan menjaga saya dengan baik. Saya dibawa ke rumahnya dan dianggap anaknya sendiri. Saya menemukan sosok ayah saya yang pergi di dalam diri om saya. Makanya saya sedih banget om saya meninggal. Saya nggak nyangka secepat ini dia ninggalin saya.”
Perasaan sedih masih begitu kental menyelimuti Muara, sampai tangis pun kembali luruh hanya dengan menceritakan kebaikan omnya. Muara menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis lebih histeris, sambil masih memegang sapu tangan milik Joval.
Kalau saja Joval sudah mengutarakan perasaannya, dia ingin memeluk Muara sekarang juga. Sayangnya dia cuma bisa mengusap-usap punggung perempuan itu, mendengarkannya menangis sampai berhenti. Joval tidak berani menyuruh Muara tabah, karena tidak ada satu pun manusia yang bisa tabah dalam waktu singkat saat sanak keluarga atau orang terkasih meninggal dunia.
“Maaf, Pak. Saya malah nangis lagi.” Muara menyeka air mata dengan sapu tangan. “Bapak masih mau di sini? Kalau pulang juga nggak apa-apa, Pak.”
“Saya tunggu di sini aja. Nggak apa-apa kalau kamu masih ingin menangis. Saya pernah kehilangan tante saya seperti kamu kehilangan om kamu. Saya mengerti perasaan kamu,” ucap Joval.
“Waktu itu om saya pernah janji mau nunggu saya sampai menikah. Dia mau nemenin saya di altar. Tapi janjinya belum terlaksana, dia udah pergi. Saya menyesal nggak menikah lebih cepat. Kalau tahu dia pergi lebih awal, saya akan mengabulkan janjinya.” Muara berucap dengan terisak-isak. Suaranya tersendat-sendat.
“Kamu nggak boleh bilang begitu. Om kamu pasti menemani kamu menikah nanti dari atas sana,” hibur Joval dengan menatap hangat Muara.
Air mata Muara terus melesak keluar. Muara tak mampu menahannya lebih lama. Joval memberikan tatapan hangat yang bisa membuatnya meluapkan seluruh kesedihannya. Dia pun menangis lagi—tidak menutup wajahnya. Muara menunduk dan menahan isak tangisnya.
Pada akhirnya Joval tidak kuat melihat Muara menangis. Dia memberanikan diri mendekatkan diri pada Muara, hingga tak ada lagi jarak yang tersisa. Pelan-pelan dia menarik kepala Muara hingga bersandar di bahunya. Dia mengusap kepala Muara sampai lebih tenang.

Joval menemani Muara | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
***
Suasana mobil sangat sunyi. Tidak ada lagi yang diputar karena Joval kurang suka suasana yang terlalu berisik. Joval lebih menyukai suasana mobil yang tenang dan sunyi.
Muara curi-curi pandangan melirik Joval. Bosnya itu sudah berbaik hati menemaninya seharian ini di rumah duka. Dia tidak enak, tapi Joval tidak mau pulang meskipun sudah diusir secara halus berulang kali. Saat para sepupunya datang pun Joval tetap menunggu. Kebetulan dia ingin berganti pakaian dan kembali lagi besok jadi bosnya itu bisa ikut pulang.
“Pak?” Muara membuka obrolan setelah cukup lama diam. Biasanya dia mengobrol dengan Joval di dalam mobil. Bertanya tentang apa pun.
“Ya?”
“Soal pertanyaan Bapak di kantor tadi, itu benar saya yang merencanakan,” aku Muara.
“Maksud kamu?” Joval melihat sekilas, bingung.
“Bapak nggak kebetulan ketemu Bu Ami. Saya dan teman-teman yang lain sengaja buat rencana biar kalian ketemu. Kami ingin kalian akur dan kalau bisa balikan biar suasana di kantor nggak dipenuhi amarah dan perdebatan nggak ada habisnya,” jelas Muara dengan jujur. Tangannya mendadak keringat dingin setelah jujur.
“Soal kopi dan surat manis, itu kalian juga?”
“Iya, Pak. Saya yang mencetuskan ide untuk menyatukan kalian. Saya dengar waktu menikah dulu Bapak sama Bu Ami adalah pasangan yang manis, makanya saya pikir ada baiknya kalian balikan lagi.”
Joval ingin mengatakan, saya maunya sama kamu, bukan balik sama Amini. Sayangnya dia tidak berani menyatakan sekarang. Kurang tepat. Kalimat yang dia lontarkan pun berbeda. “Saya sama Bu Ami nggak mungkin balikan.”
“Kenapa begitu, Pak?”
“Saya sama Amini memang nggak akan balikan lagi,” tegas Joval.
Muara diam selama beberapa menit. Bosnya itu tidak memberi tahu alasan pastinya. Dia semakin penasaran dan kemudian kembali melirik Joval yang fokus mengendarai mobil.
“Kalau boleh saya tahu, apa alasan kalian berpisah? Saya lihat Bapak dan Bu Ami cocok.” Muara bertanya dengan takut-takut. Dia tidak ingin terkesan ingin tahu kehidupan orang lain. Akan tetapi, mulut selalu berkebalikan dari keinginan.
“Ada banyak hal yang bikin saya sama dia sepakat berpisah. Kami udah pikirin matang-matang.”
Muara tidak sabar menunggu kelanjutannya. Dia ingin menyela dan bertanya terus, tapi takut dikira tukang parkir. Dia pun menunggu dengan sabar dan berharap Joval akan menceritakan sedetail-detailnya.
“Waktu itu umur kami berdua masih 22 tahun. Kami lagi giat-giatnya meniti karier. Cari tempat berkarier yang bagus biar bisa belajar tentang hukum lebih baik lagi. Kantor kami beda. Kami sering pulang malam dan jarang ngobrol saat di rumah. Kadang saya baru pulang, Ami udah tidur. Begitu sebaliknya. Kami cuma ngobrol waktu berangkat kerja, itu pun dipenuhi obrolan soal pekerjaan. Memang nggak sibuk terus, ada satu atau dua hari dalam seminggu kami senggang. Kami nggak merasa gimana-gimana waktu itu. Kami dukung satu sama lain,” cerita Joval mulai mengenang masa-masa dulu yang telah terlupakan.
“Semua baik-baik aja sampai tahun keempat pernikahan. Kami lebih sering ribut karena kurang komunikasi. Karena itu pula akhirnya kami resign dari kantor setelah udah dapat kartu advokat. Ami mencetuskan ide untuk bangun law firm sendiri. Kami ajak sahabat-sahabat kami dari SMA. Kami pikir salah paham dan pertengkaran bakal berkurang setelah satu kantor. Ternyata nggak. Kami malah sibuk-sibuknya karena dapat klien lumayan dan saat itu belum banyak pegawai. Jadi, benar-benar kewalahan urus satu kasus ke kasus lainnya. Ujung-ujungnya jadi jarang komunikasi, salah paham lagi, dan ribut lagi. Begitu terus nggak ada habisnya. Akhirnya ada titik di mana kami berdua merasa nggak bisa mempertahankan pernikahan. Kalau dipaksa, kami cuma menyakiti satu sama lain,” lanjutnya.

Perpisahan Joval dan Amini | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
Muara mendengarkan dengan saksama. Tanpa perantara alias Karmen, dia mendengar cerita alasan Joval bercerai langsung dari sang empunya kisah.
“Kami pisah baik-baik. Ami marah-marah kayak yang kamu dengar di kantor nggak bermaksud apa-apa. Mungkin itu sebagai bentuk rasa kecewanya. Saya gagal jadi suami yang baik, pengertian, dan selalu ada untuk dia. Saya nggak bisa menjadi seseorang yang memenuhi ekspektasinya.”
Muara memperhatikan Joval. Bosnya itu tampak tenang, tapi dari sorot matanya terlihat ada kesedihan. Entah apa maksudnya. Muara tidak bisa mengartikan kesedihan itu.
“Bapak udah nggak cinta lagi sama Bu Ami?” tanya Muara.
“Cinta?” ulang Joval.
“Iya. Saya dengar Bapak sama Bu Ami pacaran dari SMA terus nikah selama enam tahun. Proses pacaran kalian nggak cepat dan pernikahan kalian nggak bisa dibilang sebentar.”
Joval menarik senyum tipis. Senyum itu berubah kecut setelah menggali ingatan lebih dalam tentang masa lalu. “Setelah cerai saya masih cinta sama Ami. Biar gimana dia cinta pertama dan satu-satunya perempuan yang saya pacari. Baru beberapa hari sidang putus, dia pergi ke luar negeri tanpa pamit. Tiga bulan setelah cerai saya lihat dia mesra sama laki-laki lain. Di situ saya hancur. Saya pun tahu satu hal kalau dia nggak bahagia sama saya. Dia lebih kelihatan bahagia sama laki-laki lain,” ungkapnya.
“Jadi, Bapak menyerah gitu aja? Nggak ngejar Bu Ami lagi?”
“Iya, saya menyerah. Bukan apa-apa, dia udah pacaran sama laki-laki itu. Banyak hal yang kurang dari saya, kok. Jadi kalau dia udah nemu laki-laki lebih baik, saya nggak bisa berbuat banyak. Dia pacaran sama laki-laki itu selama empat tahun. Saya nggak tahu kenapa akhirnya putus.”
Muara terkaget-kaget. Dia tidak menduga Amini akan move on semudah itu terlepas seberapa banyak kurangnya Joval. Bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan orang yang telah bersama bertahun-tahun dengan mudahnya? Muara saja butuh empat tahun untuk move on dari mantan pacarnya yang terakhir.
“Berhubung kamu udah dengar, saya harap kamu dan yang lainnya nggak melanjutkan rencana ini. Saya sama Ami nggak mungkin bersatu lagi. Kalau pun kami ingin, udah pasti dari lama balikan. Kami udah cukup sebatas teman baik aja.”
Muara mengangguk berulang kali mengiakan ucapan bosnya. Setelah mendengar alasan kedua bosnya bercerai rasanya sulit untuk menyatukan. Apalagi setelah bercerai keduanya memang tidak pernah ada niat untuk kembali. Cerita Joval membuatnya bimbang. Haruskah dia menghentikan rencana awalnya?
Bersambung

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
Jo si pecinta cerita Misteri dan Thriller yang senang menulis Romcom. Hobinya menonton drakor dan lakorn Thailand. Jo telah menerbitkan beberapa buku di antaranya My Boss's Baby dan Main Squeeze. Karyanya yang lain bisa dilihat di IG @anothermissjo

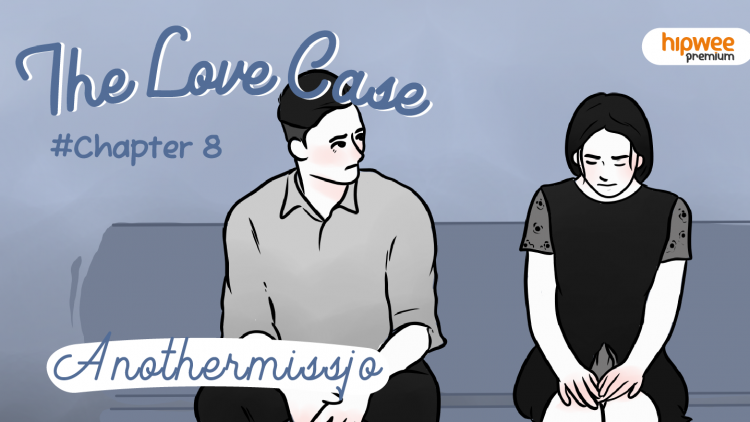








![Perfectly (Un)Matched [6] – Perfectly (Un)Matched](https://www.hipwee.com/wp-content/uploads/2022/02/hipwee-unmatched_ftr-2-160x120.jpg)


