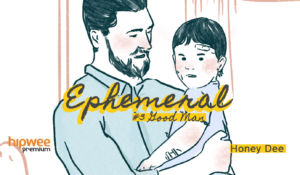Sikap Ben membuat Ivy nyaman bercerita tentang permasalahan rumah tangganya dengan Oliver. Satu demi satu kenangan ia sibak, hingga akhirnya Ivy mulai memahami dari mana semua masalah ini bermula.
***
“Aku bukan istri yang baik.”
Ben tersenyum dan bernapas dalam. “Aku suami yang amat sangat buruk.”
“Aku serius.”
“Apa kamu pikir aku bercanda?” Ben memotong kuenya dengan sendok, lalu menekan potongan kecil itu sampai gepeng, penyet menempel dengan piring. “Aku baru tahu kalau inilah yang dimaksud dengan ‘kita hanya punya kesempatan satu kali untuk mencintai seseorang’.”
Ivy tertegun menatap lelaki itu. Dia merasa lelaki itu sedang menyindirnya, bukan menceritakan tentang hidupnya sendiri.
“Apa yang terjadi pada mereka?” tanya Ivy dengan keingintahuan tinggi seperti biasa.
Ben mengunyah kue di dalam mulutnya, lalu menumpuk tangan di meja. “Tidak. Tidak,” katanya sambil tersenyum dan menggeleng sampai diikuti oleh Delilah. “Ini bukan giliranku. Ini giliranmu. Kenapa kamu mengatakan kamu bukan istri yang baik?”
“Kamu berbohong padaku,” kata Ivy serius. “Kamu bukan arsitek. Kamu pasti agen FBI. Caramu menginterogasi orang sangat mengerikan.”
Ben tergelak. Dia mendadak tertawa keras sampai Delilah terkejut dan menjatuhkan kuenya. Anak itu menangis keras. Buru-buru Ivy menggendongnya untuk menenangkannya.
“Aku akan menjadi polisi jahat yang mengikatmu di kursi. Akan kututup wajahmu dengan handuk basah dan kusiram dengan air di ember besar. Kamu akan tenggelam dalam keadaan duduk. Air akan masuk ke dalam paru-parumu dan kepalamu akan sakit sekali. Kamu akan mati perlahan karena paru-parumu penuh dengan air.”
“Hentikan!” Ivy menutup telinganya. “Tolong hentikan!”
Ben berhenti, menatap Ivy yang masih menutup telinga dengan ekspresi senang. Dia memang benar-benar senang. Sudah lama sekali dia tidak merasa sesenang ini. Sudah lama sekali dia tidak merasa senang hanya dengan melihat seorang perempuan. Di dalam dirinya ada keinginan untuk menyentuh Ivy, keinginan yang sudah lama tidak dia rasakan. Kini, dia merasa seperti mengingat lagi hal yang asing dan membingungkan. Jika boleh jujur, Ben merasa malu sekali, seperti anak sekolah yang pertama kali merasa ingin dekat dan menyentuh temannya.
Lucunya, Ivy merasakan hal ini juga. Dia berpaling mencari hal lain untuk dilakukan di dapur kecil itu atau di mana saja asal jangan duduk berpandangan dengan lelaki itu.
“Kamu tidak bekerja?” tanya Ivy setelah kehabisan alasan untuk mengelak dari Ben.
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

“Hari ini tidak. Aku punya waktu seharian untuk menunggumu berlari menghindariku.” Dia menyuapkan potongan kecil pie terakhirnya. “Dan aku sudah punya cukup energi untuk melakukannya.”
Ivy berkacak pinggang. “Kamu tidak menyerah, ya?”
Ben tertawa. “Tidak ada di dalam kamusku.”
Melihat gaya Ben dan bagaimana caranya berbicara, jelas sekali terlihat kalau lelaki itu memang tidak akan mundur, apa pun yang terjadi. Lelaki itu akan terus memaksa Ivy buka mulut, tidak peduli seberapa lama Ivy menghindar. Keteguhan di dalam mata birunya itu membuat Ivy mengerti kalau sampai sekarang dia masih memutuskan tetap mencintai istri dan anaknya juga. Keteguhan itu telah berubah menjadi kekeraskepalaan.
“Aku … pergi dari rumah suamiku,” ucap Ivy mulai membuka ceritanya.
Ben melihatnya dan memperbaiki duduknya untuk menunjukkan pada Ivy kalau dia benar-benar mendengarkan. Setelah menunggu agak lama, tapi Ivy belum melanjutkan kata-katanya, Ben berpikir untuk membantunya dengan bertanya, “kenapa?”
Ivy menggeleng, lalu menunduk. Wajahnya merah. Setelah beberapa kali menarik napas dalam dan menelan ludah, dia berkata, “Aku … tidak ingin menceritakan ini.”
“Aku tidak akan mengatakan apa pun. Aku hanya akan mendengarkan.”
“Aku marah padanya.” Ivy mengangkat wajahnya yang sudah basah karena air mata. “Aku tidak ingin mengalami nasib seperti ibuku.”
Senyum Ben hilang. Dia tahu Ivy benar-benar serius kali ini.
“Aku menikah dengannya bukan untuk mendapatkan semua ini. Aku meninggalkan semua yang kumiliki di Jakarta untuk hidup bersamanya di New York ini bukan untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Aku … ingin pulang.”
“Ke Jakarta?”
“Ya.” Tanpa sadar, Ivy meremas remot televisi yang sejak tadi dipegangnya. “Aku ingin kembali ke rumahku lagi, meninggalkan semua ini. Aku … tidak ingin bersama Oliver lagi.”
Ben menahan diri untuk tidak bertanya siapa Oliver. Dia hanya yakin kalau Oliver itu suami Ivy.
“Aku mengenal Oliver dari Instagram,” lanjut Ivy. Dia terlihat ragu sebentar, lalu menggigit bibir bawah dengan ekspresi sedang berpikir. Setelah merasa yakin dengan yang dilakukannya, perempuan itu meletakkan remot televisi dan duduk di depan Ben di meja makan. Dia memberikan sepotong kecil pie untuk Delilah, lalu melanjutkan ceritanya. “Aku mengomentari sebuah meme di akun Instagram orang yang tidak kukenal dan Oliver menimpali komentarku. Kami melanjutkan saling bertukar komentar di DM. Dia orang yang menyenangkan. Aku … suka dan terus menunggu pesannya. Aku merasa dia membuatku yakin kalau aku memiliki hidup yang menyenangkan jika aku melihat hidupku dari sisi yang lain.”
Ivy tersenyum sendiri, mengingat saat-saat dia menghabiskan malam bersama Oliver di depan layar ponsel. Dia sampai rela berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak mengantuk sama sekali atau terkena insomnia agar Oliver mau menemaninya. Padahal, dia sudah tidur lebih cepat agar bisa begadang dengan lelaki itu.
“Aku bodoh sekali. Aku tidak tahu bagaimana rupanya. Aku tidak tahu apa pekerjaannya, atau informasi lain tentangnya. Aku … hanya merasa nyaman berbicara dengannya lewat tulisan. Dia memberiku tanggapan yang menyenangkan setiap aku menceritakan sesuatu. Jika dia berpikir aku melakukan hal yang salah, dia menjelaskan kesalahanku dengan cara yang tidak membuatku merasa bersalah. Aku … benar-benar menyukainya.”
“Kamu tidak punya teman saat itu? Maksudku, teman sungguhan di sekolah atau … kampus?”
Ivy menggeleng. “Aku berteman dengan orang-orang yang salah seumur hidupku. Aku berteman dengan pengkhianat yang membuatku menangis, berteman dengan orang yang merebut pacarku, berteman dengan gadis yang akhirnya keluar dari kampus karena hamil dan sibuk dipukuli suaminya setelah menikah. Aku tidak bisa mempertahankan pertemanan sama sekali. Aku juga merasa sangat canggung saat bertemu dengan orang baru.”
“Aku memecahkan rekormu?”
Ivy tertawa. “Ya. Kamu memecahkan rekorku. Aku belum pernah cerita sebanyak ini pada orang yang baru kutemui.” Dia menggeleng cepat. “Kamu membuatku merasa bersalah.”
“Kamu ingin aku memegang tanganmu agar kamu mendapat kekuatan untuk melanjutkan cerita?” Ben membuka tangan kanannya.
Mulanya, Ivy hanya menanggapinya dengan tertawa saja, malu mengakui kalau dia memang ingin bersama seseorang. Sudah lama sekali dia ingin bercerita tentang dirinya pada orang lain. Sering, dia merasa iri melihat teman-temannya bisa bercerita tentang apa saja pada siapa saja, sekalipun pernah mendapat masalah dengan orang lain. Ivy sudah pernah mengalami pengkhianatan, teman tempatnya mencurahkan perasaan membocorkan segalanya pada orang lain. Sejak saat itu dia tidak bisa mempercayai siapa pun. Baginya, orang-orang hanya ingin tahu tentang hidupnya. Mereka tidak benar-benar ingin menyelamatkannya. Di depannya saat ini, Ben berbeda. Ben mendengarkannya, sama sekali tidak mengatakan apa pun tentang pertemuannya dengan Oliver yang aneh. Dia juga tidak mengenal Ben sama sekali. Jika nanti Ben memberi tahu orang lain, dia tidak anak mendengar apa-apa. Baginya, tidak akan ada salahnya.
Ivy mengenggam tangan Ben. “Kenapa?”
“Apa?”
“Kenapa kamu mau tahu dan memberiku tangan? Tidak semua laki-laki melakukannya.”
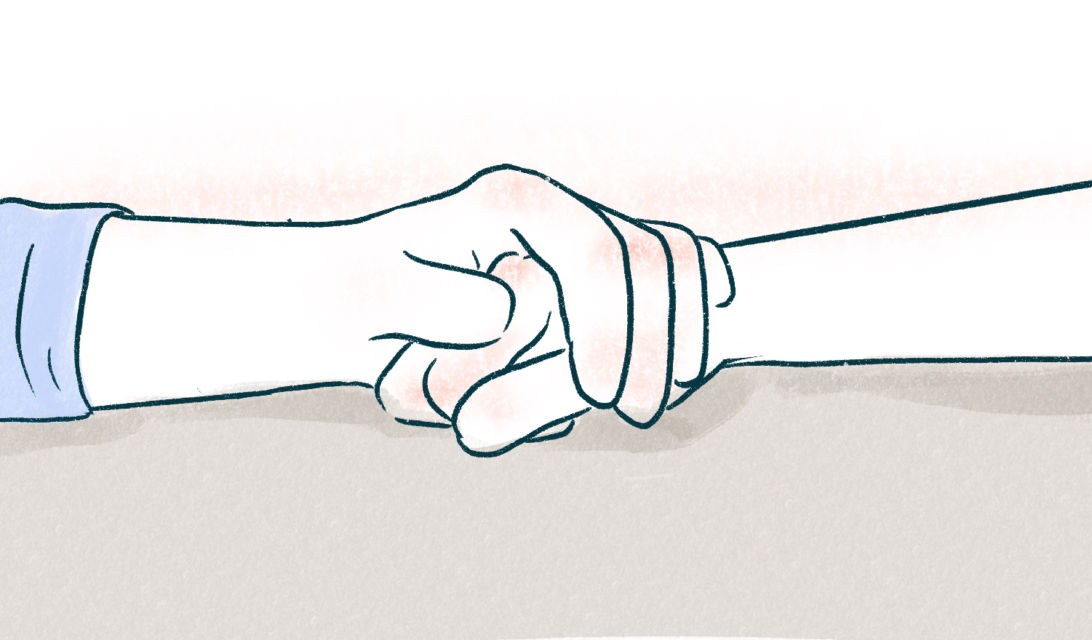
Ivy dan Ben saling menggenggam | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
Ben tersenyum lebar. Geliginya besar seperti mengimbangi bibirnya yang merah tebal di antara rambut wajahnya. “Aku hanya ingin membuatmu merasa nyaman. Kalau kamu nyaman, semua cerita akan meluncur dengan lancar, kan?”
“Tidak ada apa-apa dalam ceritaku. Yang kurasakan hanya rasa nyaman saat bersamanya. Kupikir ini hanya aku. Sudah kupikirkan saat itu kalau Oliver mungkin punya hubungan dengan orang lain dan berbohong padaku tentang banyak hal. Kamu tahu, laki-laki suka melakukannya untuk bisa tetap bersama gadis, kan?”
Ben tertawa lagi. “Ya, aku melakukannya.”
Kejujuran ini membuat Ivy tertawa juga. “Buruk sekali.”
“Parah.” Ben minum air putih beberapa teguk, lalu kembali melihat tangan di meja seperti anak sekolah. “Lalu, kamu jatuh cinta padanya?”
“Tidak. Kurasa saat itu aku belum mencintainya. Aku tidak tahu bagaimana dia. Hubungan kami berlanjut ke obrolan telepon dan video call. Dia laki-laki yang manis. Dia tidak meminta foto pornoku atau memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Dia juga akhirnya bertanya tentang kehidupanku di kampus. Aku sampai menyalakan video call saat pelajaran. Dia mendengarkan dengan baik walaupun tidak mengerti bahasa Indonesia saat itu.” Ivy terdiam saat mengingat betapa Oliver antusias menjadi satu-satunya orang yang dia percaya dan satu-satunya orang yang mempercayainya. “Aku tidak pernah melihat laki-laki semanis dia.”
Ben tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu sampai Ivy selesai dalam perenungannya sendiri. Setelah Ivy melihatnya dan tersenyum canggung lagi, baru Ben berkata, “Kalau begitu, aku bukan yang pertama.” Lelaki itu tersenyum lagi. “Kamu pernah berbicara dengan orang asing sebelumnya. Bayangkan, kamu berbicara dengan laki-laki di belahan dunia lain yang tidak kamu kenal yang bisa saja seorang anggota mafia. Dia membuatmu menceritakan di mana kamu hidup dan di mana kamu berkuliah. Kamu percaya dia alih-alih berpikir dia bisa menculikmu dan berbuat buruk padamu.”
Ivy ingin berkelit, tapi dia tahu Ben benar. “Aku memang mempercayainya. Aku tidak tahu bagaimana, aku mempercayainya. Dia … membantuku bisa berbicara lagi dengan orang lain. Dia … membantuku sampai mau mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dosen. Dia juga membantuku mempercayai orang lain dalam pekerjaan kelompok. Sebelumnya, aku … hanya duduk saja dalam kelompok, mendengarkan, setuju pada semua yang mereka putuskan, dan melakukan tugasku. Oliver yang membuatku mengatakan semua yang ada di pikiranku dan dia mendorongku untuk lebih berani. Aku mengajukan skripsi dan jadi sangat ambisius karena dia Aku menyelesaikan masa belajarku dalam waktu yang tepat, empat tahun. Dia benar-benar menemaniku selama satu tahun penuh.”
Ben bertepuk tangan sambil menggeleng takjub. “Luar biasa!”
“Ya. Dia luar biasa.” Ivy menghapus air matanya. “Setelah kelulusanku, dia bertanya apa yang ingin kulakukan. Aku bingung sekali. Aku tidak punya mimpi Aku hidup hanya karena harus hidup. Aku ingin keluar dari rumah ibuku. Kupikir, ibuku mengizinkanku untuk bekerja di tempat lain dan keluar dari rumahnya. Ternyata tidak. Ibuku tetap ingin aku tinggal di sana. Satu-satunya cara aku keluar dari rumah itu adalah dengan menikah. Aku … tidak punya siapa pun untuk kunikahi. Aku sendirian. Satu-satunya lelaki yang kukenal hanyalah Oliver. Lalu, Oliver bertanya apa aku ingin menikah dengannya. Kukatakan padanya kalau aku mau saja. Dia tampan dan anakku pasti akan sangat cantik.”
Ben melihat Delilah dan mengangguk. “Kamu benar-benar mengerti cara menerapkan ilmu genetika. Anakmu luar biasa cantik.”
Ivy tertawa sambil menghapus air matanya. “Oliver melakukan hal yang kupikir hanya bisa kulihat di film dan novel saja. Dia datang ke Indonesia. Dia menyeberangi samudera untukku. Dia mengatakan kalau dia tidak punya pilihan lain di dunia ini selain menikahiku. Kupikir, dia hanya membual. Dia hanya sekadar orang yang ingin menghiburku. Saat dia menunjukkan foto-foto sedang berada di negara-negara yang disinggahi sebelum sampai ke Indonesia, aku sempat berkata kalau dia mengedit fotonya. Ternyata, dia benar-benar mengetuk pintu rumah ibuku dan mengatakan kalau dia mencintaiku. Dia ingin menikahiku, tidak peduli apa pun yang harus dia hadapi. Saat itu aku merasa menjadi gadis paling bahagia di dunia. Aku melawan semua kata-kata keluargaku yang melarangku menikahinya. Aku mendapatkan tiket untuk keluar dari rumah ibuku, dari kehidupan lamaku untuk bersamanya.”
Delilah menangis dan merengek karena merasa tidak nyaman. Ivy berdiri untuk memeriksanya. Ternyata, anak kecil itu bau sekali. Ben sampai tertawa sambil mengerutkan hidung. Buru-buru Ivy membawanya ke kamar mandi sambil berusaha menenangkan Delilah.
Lelaki itu melihat sosok belakang Ivy yang masih memakai celemek dan anaknya, membayangkan orang lain yang melakukannya, orang dari masa lalunya. Cerita Ivy juga mengingatkannya pada masa lalu, saat dia bertemu dengan gadis itu, gadis berambut cokelat yang berkata kalau dia sudah terlalu lelah hidup dengan pacarnya saat ini.
“Apa kamu tahu kalau menjadi pemburu itu pada titik tertentu jadi tidak lagi menyenangkan? Kamu berburu dan mendapatkan buruan. Kamu lelah saat tahu kalau buruanmu itu ternyata tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu kesal, lalu pergi lagi untuk mencari buruan baru. Kamu menginginkan hal lain yang lebih menantang. Sayangnya, kamu tidak tahu apa yang membuatmu tertarik,” kata gadis itu sambil membolak-balik gelas kertas berisi koktail-entah-apa yang rasanya seperti air cucian piring dengan banyak alkohol.

Ben mengingat pertemuan pertamanya dengan Sheila | ilustrasi: Hipwee
“Lalu, apa yang kamu inginkan? Jujur saja, aku tidak pernah sengaja berburu. Aku hanya menjalani hidupku, makan, dan minum seperti manusia pada umumnya. Aku tidak mencari apa pun.” Kemudian, Ben tersenyum saat mendapatkan tanggapan “membosankan” sambil memutar mata dari gadis itu.
“Baiklah, dari pakaianmu yang rapi, bisa kutebak kamu masih tinggal dengan ibumu dan ibumu juga yang merapikan semua yang kamu pakai.”
“Ya. Ibuku mengalami dementia dan dia hanya memilikiku. Saat ini aku tidak berencana mengikuti pesta ini. Aku hanya ingin mengembalikan mobil yang kupinjam pada Adam Rockwood. Kamu temannya?”
“Tidak. Laki-laki itu meniduri semua temannya. Semoga Tuhan menjauhkanku dari laki-laki seperti dia.” Perempuan itu membuat simbol salib pada tubuhnya yang membuat Ben tergelak. “Aku ke sini bersama temanku. Dia teman Adam, tapi aku yakin Adam tidak akan menidurinya.”
“Kenapa?”
“Karena dia laki-laki.”
Tawa mereka inilah yang menjadi pembuka obrolan mereka kemudian. Sheila Browning memberikan warna baru dalam hidup Ben yang hanya berkisar Rockwood Building dan rumahnya. Ben merupakan tempat pemberhentian yang sempurna untuk perburuan Sheila, gadis petualang dengan hati lembut. Mereka menikah tiga bulan setelah mereka bertemu dan Ben benar-benar menyesalinya. Dia merasa terlalu terburu-buru. Dia tidak mengenal apa pun tentang Sheila dan Sheila sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang Ben. Saat berada di depan altar, mereka sama sekali tidak tahu kalau mereka sedang mempersiapkan bom waktu untuk menghancurkan hidup mereka.
“Maaf sudah membuatmu menunggu lama,” kata Ivy sambil menggendong Delilah yang baru selesai mandi.
Ben yang sebenarnya terkejut tersenyum saja. Lelaki itu mengangguk, mempersilakan Ivy menyelesaikan urusan dengan anaknya. Dia membereskan piring kotor dan membawanya ke tempat cuci piring. Namun, tidak lama, Ben tertegun. Dia mendengar suara Sheila di dalam kepalanya, “Tidak bisakah kamu membantuku walau hanya sedikit, Ben? Apa aku benar-benar harus menyelesaikan semua ini? Apa kamu tidak bisa sedikit pun merasa peduli pada kami?”
Seberapa banyak pun dia mengucapkan maaf, suara itu akan tetap ada di dalam kepalanya. Suara itu menggema keras, menyuarakan rasa sakit yang terlalu dalam dia goreskan pada hati perempuan yang paling dia cintai.
“Ben?” panggil Ivy pelan. “Apa kamu baik-baik saja?”
Ben berbalik untuk mengatakan kalau dia baik-baik saja, tapi dia tidak bisa. Delilah memakai baju Ravenna. Rambut Delilah juga dikuncir dua seperti Ravenna. Bedanya, Ravenna pirang mengikuti warna rambut neneknya. Ben berusaha keras untuk tetap tersenyum. “Cantik sekali,” katanya dengan dada bergetar.
“Terima kasih. Pakaian ini bagus sekali. Semuanya nyaman dipakai oleh anak-anak.”
Ben mengangguk saja. Dia menuju meja dan menghabiskan kopi yang baru diminumnya setengah. Kepalanya tiba-tiba merasa sakit lagi. Sudah berbulan-bulan dia tidak merasakan sakit ini. Seharusnya dia mendengarkan kata hatinya untuk tidak memberikan pakaian milik Sheila dan Ravenna.
Ivy menurunkan Delilah, membiarkan anak itu bermain dengan boneka yang dberikan Ben saat mereka di rumah sakit. “Kamu teringat sesuatu? Apa ada pekerjaan yang harus dilakukan?” tanya Ivy lagi. “Ben?”
Lelaki itu geragapan. “Tidak. Tidak ada,” jawabnya dalam usaha keras untuk menguasai diri. Dia duduk di sofa di depan televisi.
“Aku akan membuatkanmu kopi lagi.”
“Ya. Kurasa aku membutuhkannya. Terima kasih.”
Setelah kopi panas itu datang dan Ben meminumnya sedikit, dia tidak merasa lebih baik. Sebaliknya, dia merasa makin tidak baik-baik saja. Sheila juga memberinya kopi yang terlalu panas. Sheila juga tidak pernah memberinya gula agar dia mengambil sendiri takaran gula yang dia inginkan.

Kopi yang dibuatkan Ivy membuat Ben semakin teringat Sheila | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
“Ben, apa kamu mau tahu apa yang terjadi setelah kami menikah?” tanya Ivy yang disambutnya dengan wajah cerah.
“Tentu saja. Aku menunggu-nunggu ceritamu.” Dia tahu dia membutuhkan cerita itu. Dia membutuhkan segalanya yang bisa mengalihkan pikirannya dari masa lalu.
“Aku … bahagia. Oliver memberikan semua yang kuinginkan. Dia mengganti agama agar sama dengan agamaku, bersedia tinggal di rumah ibuku walau rumah ibuku sempit dan jelek, juga berusaha mengenal keluarga besarku. Dia memberikan uang yang banyak untuk biaya pernikahan seperti yang pernah kujelaskan padanya. Dia menjadi suami yang benar-benar mengerti tentang keluarga istrinya.”
“Sempurna,” kata Ben sambil menyesap kopi panasnya lagi.
“Ya, sempurna sampai aku hamil. Aku positif hamil tiga minggu setelah menikah. Semua orang membicarakan kami. Mereka pikir kami telah berhubungan seksual sebelum menikah.”
“Lalu?”
Ivy memperbaiki duduknya untuk berbicara dengan lebih serius. “Begini, Indonesia sangat berbeda dengan Amerika. Di sana, budaya berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang terlarang. Gadis-gadis yang tidak bisa mempertahankan keperawanan masuk dalam kategori gadis nakal. Aku yang tidak pernah punya pacar seumur hidupku tentu saja masih perawan, tapi mereka pikir selama satu bulan masa persiapan pernikahan itu Oliver telah meniduriku. Mereka begitu menyalahkan Oliver dan aku. Untuk Oliver yang tidak fasih berbahasa Indonesia, cibiran mereka tidak akan terasa berat, tapi bagiku, semua itu rasanya seperti siksaan.”
Ben menggeleng tidak setuju. “Kalian sudah menikah, kan? Seharusnya, apa pun yang kalian lakukan … tetap saja kalian sudah menikah.”
“Mereka tidak mau peduli. Mereka memang ingin merisak siapa pun yang salah. Mentertawakan kesalahan orang lain dan membicarakannya membuat mereka merasa suci. Selamanya, aku menjadi contoh buruk bagi semua anak di keluarga besarku.”
“Sangat tidak adil.”
“Kami bertahan selama tiga bulan di rumah ibuku, lalu aku memohon untuk pergi. Aku tidak ingin jadi gila di lingkungan itu. Kami tinggal di apartemen yang jauh dari mereka. Kami memperbaiki semuanya dan berusaha belajar menjadi orang tua yang baik untuk calon anak kami. Sayangnya, kami tidak bisa. Sampai kapan pun kami tidak bisa. Oliver seperti ketakutan setelah melihat Delilah lahir. Dia menghindari Delilah. Ini aneh sekali. Dia tidak ingin membicarakannya denganku.”
“Dia termakan omongan keluargamu?”
“Tidak. Kami nyaris tidak berkomunikasi dengan mereka. Hanya ibuku dan ibuku sudah berjanji untuk tidak mengungkit apa pun setelah aku bersumpah tidak melakukan apa pun sebelum pernikahan.” Ivy mengingat-ingat lagi semua yang dilakukan Oliver sejak kelahiran Delilah. “Dia tidak peduli apa pun tentang Delilah. Dia hanya melakukan segalanya untukku, tapi tidak ingin menyentuh anaknya sama sekali. Ini membuatku sangat patah hati. Kamu tahu rasanya hamil selama sembilan bulan dan melahirkan bayi? Sakit. Yang kurasakan hanya sakit. Aku ingin paling tidak dia mengatakan kalau dia mencintai Delilah. Aku ingin dia memberikan sesuatu pada Delilah karena Delilah anaknya. Aku tidak ingin Delilah mengalami yang kurasakan. Lalu, saat Delilah sudah satu setengah tahun, aku bertanya apa dengan kembali ke New York dia bisa membuat segalanya jadi lebih baik. Dia menyetujuinya dan … astaga! Oh, astaga!”
Ivy menutup mulutnya dengan tangan. Dia teringat banyak hal, terutama saat Oliver berkata, “Aku tidak melihat ada hal baik yang ada di sana, Ivy. Di sana hanya ada masa lalu. Aku khawatir kita hanya akan merusak segalanya.”
“Ivy?” panggil Ben pelan. “Apa kamu baik-baik saja?”
Ivy melihat Ben dengan tatapan nelangsa. “Ternyata, aku yang menghancurkan semuanya,” bisiknya sebelum tenggelam dalam tangisan.
-Bersambung-
Baca bab selanjutnya: Ephemeral #8 – If You Only Knew

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
Penulis yang telah menghasilkan lebih dari 30 judul karya ini masih berusaha menjadi orang baik. Kalau bertemu dengannya di media sosial, jangan lupa tepuk bahunya dan ingatkan kalau dia juga butuh pelukan.