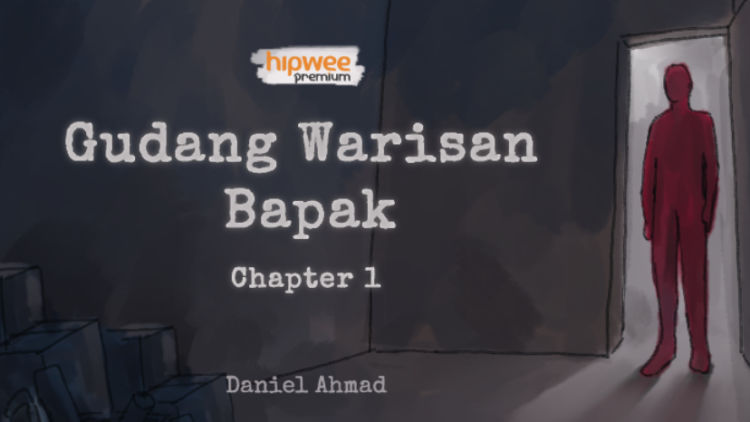Situbondo, 2014
“Zara, kamu harus pulang dulu. Bapak sakit.”
Masih kubaca berulang-ulang pesan singkat dari Kak Sabit. Bahkan saat bus yang membawaku pulang ke Situbondo sudah hampir sampai, tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkannya. Aku adalah satu-satunya anak tiri di keluarga, satu-satunya pula yang tidak terlalu dianggap sejak meninggalnya ibu empat tahun lalu. Lantas kenapa saat bapak sakit, semua kakak tiriku bergantian memintaku pulang? Tidak mungkin kalau bapak tiba-tiba ingat pada putri dari perempuan yang ia nikahi lalu ia telantarkan hingga ujung hayat.
“Perempatan Panji!”
Lamunanku terhenti. Kernet bus sudah membuka pintu. Kujejakkan kaki di bumi Situbondo setelah kurang lebih empat tahun tidak pulang ke sini. Tidak banyak berubah. Retakan di gapura merah itu masih sama. Toko obat di seberang jalan juga masih belum mengganti spanduknya yang sudah luntur karena sinar matahari. Yah, aku pergi cuma empat tahun. Waktu yang singkat untuk sebuah kota kecil yang perkembangan pembangunannya tak secepat di ibu kota.
Rumahku masih 500 meter melewati gapura merah itu, terus ke utara sampai pemukiman warga yang berjajar di kanan dan kiri jalan, berakhir menjadi ladang jagung. Rumahku ada di paling ujung. Sedikit terpisah dari rumah-rumah lainnya.

Rumah di ujung/ Illustration by Hipwee
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

“Zara!”
Pria gondrong yang duduk di motor bebeknya, di samping gapura itu melambaikan tangan. Dari seberang jalan pun aku bisa mengenalinya.
“Kak Rohim?”
Setelah tolah-toleh, aku menyeberang. Kak Rohim tersenyum menyambutku. Tak ada ucapan selamat datang atau basa-basi apa pun. Ia langsung memintaku naik ke motor dan kami pun berangkat.
100 meter pertama kami lalui dengan canggung. Saling diam. Aku tak tahu harus bicara apa pada kakak tiriku yang paling muda ini. Ia juga tampak sibuk mengendarai motor sambil main ponsel.
“Kamu cuma bawa barang sedikit, Ra?” Tanya Kak Rohim.
“I-iya, Kak. Kan cuma dua atau tiga hari,” jawabku. Kenapa juga aku jadi canggung bicara dengan Kak Rohim? Bukankah dia satu-satunya saudara tiri yang dekat denganku dari dulu? Usia kami juga tidak terpaut jauh.
“Emang Kak Sabit nggak ngomong sama kamu, ya, Ra?”
“Ngomong apa, Kak? Kak Sabit, Kak Imah, Kak Naura, semuanya cuma minta aku pulang soalnya bapak sakit.”
Tak ada jawaban lagi dari Kak Rohim. Kulihat dari spion motor, tampaknya ia bingung. Wajah bingungnya membuatku ikut bingung. Seperti ada sesuatu yang tidak dikatakan padaku.
Kami melanjutkan perjalanan dengan obrolan seadanya. Basa-basi kehidupan mahasiswi yang hidup di kota, kemudian cerita tentang seorang buruh pabrik yang hidup di desa. Berkali-kali Kak Rohim bilang kalau aku beruntung bisa dapat beasiswa untuk kuliah, lalu membandingkan dengan nasibnya yang menurut dia sangat bertolak belakang.
Ladang jagung sudah terlihat di kejauhan. Tak lama kemudian, kami sampai di rumah, dan tercenganglah aku. Saat tadi kurasa kota kecil ini tak banyak berubah, rumahku justru berubah sampai tak aku kenal. Ke mana perginya tanaman hias dan bunga-bunga yang dulu berjajar di teras? Apa yang terjadi pada dinding rumah bercat putih tulang yang kini kusam dan menghitam? Lalu, apa maksud dari plang kayu yang dipasang di pintu, jendela, dan ventilasi rumah?
“Ayo, Ra. Ngapain bengong?”
Kak Rohim sudah menjinjing tasku ke teras. Tak memberiku waktu untuk berpikir tentang perubahan yang nyaris total ini. Kuikuti saja. Akan ada penjelasan rinci di dalam rumah nanti. Semoga.
Begitu pintu rumah dibuka, aku disambut sensasi asing yang sama sekali tak mengingatkanku pada rumah. Almarhum ibuku menikahi bapak saat aku berusia 8 tahun, sejak saat itu aku tinggal di sini. Rumah ini punya ikatan yang lebih dalam dengan masa kecilku dibanding rumahku sendiri. Namun, sekarang tak bisa kupercaya rumah kosong tanpa perabotan ini adalah tempatku tumbuh dewasa. Ini lebih mirip gudang. Gelap, karena jendela ditutup rapat, bahkan dipasangi papan kayu dari luar. Pengap.

Ruangan pengap/ Illustration by Hipwee
Ruang tamu tempatku biasa membaca buku, kini hanya ruang kosong dengan karpet hitam yang hanya menutupi separuh lantai. Itu pun aku yakin, kalau karpet ini dulunya berwarna putih. Entah apa yang membuatnya jadi hitam seperti disiram satu galon kopi.
“Kamarmu di sini,” kata Kak Rohim seraya membuka pintu kamar yang berada di ruang tamu.
“Kamarku yang dulu?” tanyaku.
“Sudah jadi gudang, Ra.”
Aku tak berharap bisa tidur di kamarku yang dulu, tapi kenapa harus jadi gudang? Gudang di dapur buat apa?
Beruntung kamar yang disiapkan untukku tidak terlalu buruk. Rapi. Seprainya bersih. Dindingnya juga tidak kotor seperti dinding lain di rumah ini. Masih tercium bau cat. Kalau boleh mengeluh, maka aku keluhkan lampunya. Ini siang hari, tapi aku harus menyalakan lampu karena jendela kamar ditutup rapat. Tak ada cahaya yang masuk.
Kak Rohim meletakkan tasku di lantai.
“Kamu istirahat saja dulu,” katanya.
“Bapak mana, Kak?”
Tiba-tiba air muka Kak Rohim berubah masam. Ia mencoba memalingkan pandangan, tapi karena aku ada di hadapannya, menunggu, ia pun tak punya alasan untuk tidak menjawab.
“Bapak ada di belakang. Kamu … mau ketemu?” Tanya Kak Rohim.
Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku mau ketemu. Bukankah itu alasan aku disuruh pulang? Bukankah bapak sakit keras dan katanya setiap malam selalu memanggil namaku? Aku mengangguk, lalu Kak Rohim mengantarkanku ke belakang. Kami melewati kamar ibu dan bapak—dulu, sekarang entah siapa yang menempati.
Kata Kak Rohim, kamar bapak yang baru ada di belakang, di dapur. Meski seingatku di sana tidak ada kamar. Kondisi rumah ini benar-benar miris. Aku seperti diajak ke rumah kosong yang sudah lama diabaikan. Tak tahu lagi ini kamar siapa, dapur yang mirip kandang ayam, dan musala yang penuh tumpukan karung.
“Sini, Ra!”
Terjawablah sudah kenapa kamarku yang lama jadi gudang, ternyata gudang di dapur sekarang jadi kamar bapak.
Ruang yang kecil, hampir sama kecil seperti kamar mandi. Kutatap tajam Kak Rohim. Heran sekaligus marah. Kenapa bapak yang sudah tua harus tinggal di gudang?
Kak Rohim mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia pun mempersilakan aku untuk mencoba sendiri. Kuketuk pintu kamar yang terbuat dari tripleks itu, seraya dengan lembut memanggil bapak.
“Assalamualaikum, Pak. Ini Zara, Pak.”
Sama seperti sebelumnya. Aku tak mendengar jawaban. Aku menoleh pada Kak Rohim, dia hanya mengangkat bahu.
Tak lama kemudian, terdengar suara berisik dari dalam kamar. Seperti suara benda bergetar, bergerak-gerak dengan cepat, berpadu dengan suara benda jatuh ke lantai. Pintu tripleks pun sampai ikut bergetar.
“Bapak?” kudekatkan telinga ke daun pintu.
Suara barusan semakin jelas terdengar. Gaduh sekali, sampai tiba-tiba sesuatu membentur pintu dari dalam. Aku terperanjat sampai menjerit.
“Ayo, Ra,” kata Kak Rohim.
Kak Rohim menggamit tanganku, lalu membawaku pergi dari dapur dengan terburu-buru. Sampai di ruang tamu pun Kak Rohim masih tampak gelisah. Ia menoleh ke arah dapur, seolah memastikan tidak diikuti oleh seseorang.
“Oke, sekarang jujur sama aku, ada apa sebenarnya? Bapak sakit apa? Rumah ini kenapa? Dan … kakak kenapa?” tanyaku. Tak tahan lagi dengan segala misteri yang menyambutku. Tubuhku masih lelah setelah perjalanan jauh. Aku sedang tidak bernafsu main tebak-tebakan.
“Sabar ya, Ra. Tunggu Kak Sabit datang. Biar Kak Sabit yang jelaskan. Sekarang aku pulang dulu, sebentar lagi aku masuk kerja.”
“Lo, nggak bisa gitu dong, Kak. Kasih tahu aku dulu, siapa yang ada di gudang? Pasti bukan bapak, kan?”
Kak Rohim memegang pundak kiriku. Wajahnya tampak ketakutan. Dengan suara bergetar ia mencoba meyakinkanku.
“Itu bapak. Bapak kita,” kata Kak Rohim. “Tolong, Ra. Posisiku sulit. Aku … aku nggak mau salah bertindak, jadi sekarang kamu istirahat saja dulu. Nanti Sore Kak Sabit pasti ke sini. Biar dia yang jelasin semuanya, ya,” tutur Kak Rohim.
Tanpa menunggu jawabanku, Kak Rohim langsung berlalu. Ia pergi. Motor bebek itu meninggalkan halaman rumah, dan tak sedikit pun Kak Rohim menoleh padaku yang termangu di pintu.
***
Pukul 8 malam. Kak Sabit tak juga datang. Teleponku tidak dijawab. Bukan hanya Kak Sabit, semua saudara tiriku seolah menghindar. Sejak siang sampai sekarang aku sibukkan diri dengan membersihkan rumah. Menyapu, mengepel, dan mencuci seprai, karpet, taplak meja, apa pun yang bisa kubersihkan, kubersihkan.
Aku juga menemukan banyak sekali keanehan di rumah ini. Ranjang dan lemari di kamar ibu dan bapak yang lama sudah tidak ada. Kalender yang terpajang di dinding adalah kalender empat tahun lalu, sama seperti mi dan kopi instan di lemari, semuanya kedaluwarsa. Kamar lamaku yang katanya jadi gudang sekarang terkunci rapat. Jangan tanyakan soal bau, hampir di setiap sudut rumah aku mencium aroma pesing. Asumsiku rumah ini tak pernah dikunjungi selama kurang lebih empat tahun, karena terakhir kali aku ingat, semua masih baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah ibu meninggal dan setelah aku meninggalkan rumah ini.
Aku memikirkan bapak. Ia tak keluar kamar sejak aku datang. Itu artinya bapak belum makan. Aku juga mulai lapar. Kalau tahu kondisinya begini, harusnya tadi aku belanja. Sekarang sudah malam. Aku tidak mau jalan kaki ke warung yang belum tentu masih buka. Belum lagi tabung gas di rumah ini kosong. Roti, camilan dan air mineral bekal perjalananku sudah kuletakkan di dapur. Siapa tahu bapak bangun, ke luar kamar karena lapar.
Lelah mengalahkanku. Aku tertidur di kursi panjang di ruang tamu, dan baru terjaga saat mendengar suara berisik dari arah dapur.
“Bapak?”
Itu yang pertama kali terpikirkan olehku. Cepat aku bangun lalu pergi ke dapur, dan benarlah dugaanku, seseorang sedang makan roti di dapur. Di lantai. Tapi, itu bukan bapak. Setidaknya tidak tampak seperti bapak. Baru kusadari saat mencoba menghidupkan lampu, ternyata lampu di dapur mati. Sosok kurus itu sedang duduk jongkok di lantai sambil membelakangiku, makan roti seperti … seperti hewan. Ia tak mengenakan baju, hanya celana pendek berwarna cokelat. Satu-satunya yang membuatku masih merasa kalau itu bapak adalah bekas luka di punggungnya. Itu bekas luka waktu bapak kecelakaan dulu.

Bapak?/ Illustration by Hipwee
“Ba-bapak,” panggilku.
Ia tak menoleh. Suaraku yang pelan kalah oleh suara mengunyah roti yang terlampau lahap dan sedikit menjijikkan.
Aku mendekat. Pelan. Lantai dapur di rumah ini terbuat dari semen. Berbeda dengan lantai lainnya yang menggunakan keramik. Terasa sekali dinginnya menyentuh telapak kakiku.
Kini jarakku dan jarak bapak tinggal tiga langkah, dan anehnya aku tak berani mendekat. Entah karena gelap, entah karena aku masih merasa tak mengenali bapak lagi, atau … karena ada seseorang yang sedang berdiri di pintu kamar bapak. Sosok yang besar. Tinggi. Badannya nyaris menutupi bingkai pintu. Kalau mataku tak salah lihat, ia juga tak mengenakan sehelai pakaian, anehnya dari tempatku berdiri, kulit sosok itu terlihat berbeda dengan kulit manusia pada umunya. Warnanya merah gelap. Aku tak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajahnya.
“Zara.”
Aku terpengarah karena tiba-tiba bapak sudah berada di hadapanku. Wajah bapak kurus sekali. Pucat. Pipinya cekung. Lingkar matanya menghitam. Ia menengadahkan tangan.
“Bapak, lapar,” katanya.
Belum sempat aku menjawab, kudengar suara orang memanggilku dari ruang tamu. Suara Kak Sabit.
“Tu-tunggu di sini, Pak. Kak Sabit datang. Zara sudah minta dibawakan makanan.”
Usai berkata demikian, aku langsung pergi ke ruang tamu. Langkahku cepat. Tidak, bukan sekadar cepat. Aku berlari. Aku takut. Entah takut pada sosok di pintu kamar bapak, atau aku takut pada bapakku sendiri? Yang jelas, sesuatu telah terjadi pada bapak, pada rumah ini, dan satu-satunya orang yang bisa memberiku jawaban adalah Kak Sabit.
-bersambung…

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
Penulis novel Midnight Restaurant, Midnight Hospital, Post Meridiem dan Timur Trilogi.