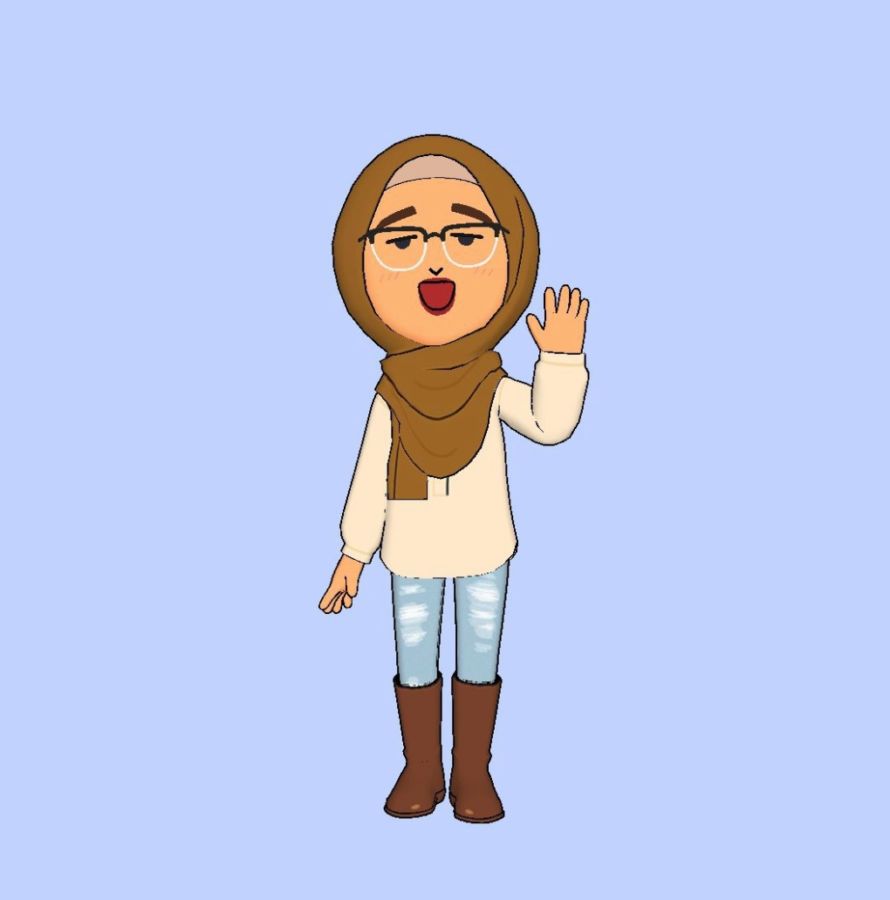To love someone so much
To have no control
You said, “I want to see the world”
And I said, “Go”
(Lost Without You – Freya Ridings)
***
“Jadi, kita ke mana lagi?” tanyaku sembari mengekor di belakang Thomas.
Thomas membukakan pintu Sabang16 untukku, mempersilakanku keluar duluan sebelum menyusulku. Dia tersenyum penuh misteri saat bersitatap denganku.
“Masih dalam misi membuatmu mengurungkan niat untuk memutuskanku.”
Sontak langkahku terhenti saat mendengar penuturan itu. Aku membeku di tempat.
“Tapi sebelumnya kita balik ke indekosmu dulu, ya. Aku numpang mandi.” Thomas berkata enteng.
Aku menghela napas panjang. “Kenapa harus diperumit, sih, Mas?”
Secuil tawa kecil meluncur dari bibirnya. Thomas mengacak rambutku yang pagi ini dalam keadaan lepek akibat belum keramas sejak kemarin, juga karena keringat. Meski enggak bisa dibilang sukses, lari pagi tadi cukup membuat keringatku mengucur.
“Because it’s you. Selama berurusan denganmu, enggak pernah ada yang simpel, Sha.”
“Kamu enggak perlu lakuin apa-apa, karena pada akhirnya kamu akan sadar kalau sebaiknya kita memang berpisah,” elakku.
Thomas menyeka keringat yang menggumpal di keningnya dengan ujung baju. “Lima tahun ini terlalu berharga buat berakhir tanpa perjuangan, Sha.”
Aku menghela napas. “Kamu rumit.”
“Ketularan kamu kayaknya,” sahut Thomas sambil terkekeh. Thomas meraih tanganku dan mendorong punggungku pelan untuk masuk ke mobil. Sekilas, dia mengecup puncak kepalaku ketika aku merunduk untuk masuk ke mobil. “Kamu rumit, tapi aku suka.”
ADVERTISEMENTS
Kamu sedang membaca konten eksklusif
Dapatkan free access untuk pengguna baru!

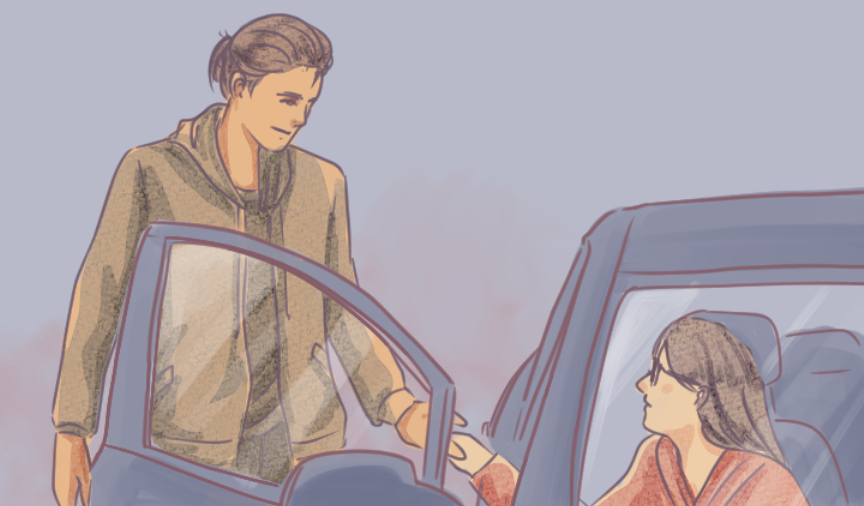
Thomas membukakan pintu mobil untuk Sasha | Ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
Sasha si rumit. Itu julukan yang ditujukan untukku, seringnya untuk meledek. Aku sempat mengingkarinya, tapi akhirnya aku menerima kenyataan kalau pola pikirku seringkali memiliki jalanan bercabang-cabang yang kadang sulit untuk dimengerti. Bahkan oleh diriku sendiri.
Sementara Thomas, si ringkas, karena paling anti berbelit-belit dan selalu straight to the point. Entah bagaimana dia bisa mengikuti semua kerumitanku selama ini.
Ketika Thomas memintaku menjadi pacarnya, aku tidak langsung menerima. Total, kami baru bertemu lima kali. Dua di antaranya berupa ketidaksengajaan. Setelah bertukar pin BBM, Thomas mengajakku jalan, langsung mengakui kalau dia tengah melakukan penjajakan.
Di kencan ketiga, Thomas memintaku menjadi pacarnya.
“Menurutku ini terlalu cepat. Kita baru nge-date tiga kali, seberapa besar keyakinanmu kalau hubungan ini akan berhasil?” tanyaku kala itu.
“Tadinya mungkin 80%, tapi melihat tanggapanmu, keyakinanku bulat jadi 100%,” jawab Thomas.
“Why?”
“Karena kamu enggak langsung menolakku. Artinya, kamu juga punya rasa, tapi mungkin masih denial.”
“Tahu dari mana kamu kalau aku punya rasa?” cecarku.
“Kalau enggak ada rasa, kamu akan langsung menolak. Tapi ini, sudah sepuluh menit, dan aku belum menerima penolakan,” sahutnya tegas.
“Mungkin kamu akan menerima penolakan di menit kelima belas.”
“Mungkin juga kita resmi pacaran di menit kelima belas,” bantahnya.
Aku tertawa kecil. “Aku enggak punya keyakinan kalau hubungan ini bisa berhasil.”
“Kenapa enggak?”
Bersamaan dengan satu helaan napas panjang, aku mengangkat pundak. “Kita belum terlalu mengenal.”
Thomas mengulurkan tangannya di atas meja yang membatasi kami lalu menggenggam tanganku erat. “Setiap keputusan selalu punya kesempatan 50:50. Hubungan ini berhasil? 50:50. Hubungan ini gagal? 50:50. Tergantung nanti kitanya gimana saat menjalaninya.”
Life is about a 50:50 chance. Apa pun yang terjadi dalam hidup selalu berada dalam perbandingan tersebut. Apakah nantinya berubah, tergantung proses menjalani keputusan tersebut.
Menginjak tahun kelima menjalin hubungan dengan Thomas, kupikir kalau kesempatan 50:50 itu sudah berubah menjadi 100%. Namun, ketika aku memikirkan masa depan dan hanya kegamangan yang kurasakan, kesempatan itu berkurang hingga tidak ada yang tersisa.
At the end of the day we will have a different path.
“Masih ada tempat kosong enggak di kopermu?”
Pertanyaan Thomas memupus lamunanku, mengembalikanku ke masa sekarang. “Masih, kenapa?”
Alih-alih menjawab, Thomas malah memarkir mobilnya. Aku menatap ke luar jendela, pandanganku tertumbuk pada deretan toko di pinggir jalan yang menjual barang antik.
Jalan Surabaya. Another memory of me and him.
“Aku belum ngasih hadiah buat dibawa ke Edinburgh,” ujar Thomas. Dia sudah mematikan mesin mobil dan membuka kunci otomatis. “Yuk, ini kan tempat favoritmu.”
Sejenak, aku bergeming di tempat. Mataku terpaku pada deretan toko di luar, sementara kepingan kenangan demi kenangan berhamburan menyesaki benakku.

Toko-toko barang antik di Jalan Surabaya | ilustrasi: Hipwee via www.hipwee.com
Thomas membukakan pintu untukku, sehingga lagi-lagi dengan berat hati aku turun dari mobil.
“Panas, Mas. Lengket gini, enggak nyaman buat belanja,” keluhku.
Thomas tertawa kecil. “Sebentar aja. Aku mau ngasih hadiah buatmu, biar kamu ingat kalau di sini ada yang sayang sama kamu. Biar enggak kegoda sama bule Edinburgh.”
“We’re over,” ingatku.
“Not yet,” sanggahnya, dengan tatapan serius yang menusukku.
“Cukup aku aja yang rumit, Mas. Kamu jangan.”
Thomas tidak lagi menyanggah ucapanku. Dia menggenggam tanganku di sepanjang trotoar dan memasuki toko barang antik pertama yang kami lewati.
Aku yang memberitahu Thomas soal kesukaanku terhadap barang antik. Aku bukan pecinta seni, dan aku juga enggak sekaya itu untuk menjadi kolektor barang antik. Lebih tepatnya, aku menyukai barang tua, atau terpaksa menyukai barang tua yang sudah akrab denganku sejak kecil.
“Jamnya lucu,” ujar Thomas sambil menunjuk jam antik yang ukurannya lumayan besar.
“Koperku enggak muat. Lagian, pasti ribet bawa jam segede itu,” bantahku.
Thomas tertawa. “Aku masih nyimpan jam yang kamu kasih. Ada di kontrakanku di Banda Aceh.”
Aku memberinya hadiah berupa jam antik yang mirip dengan punyaku di hari ulang tahunnya empat tahun lalu. Tidak lama setelah kami merayakan anniversary pertama.
“Biar kamu ingat aku terus,” ujarku kala itu.
“Kamu juga punya pajangan ini bukan?” tanya Thomas sambil menyodorkan dua patung pewayangan berukuran kecil.
Aku menggeleng. “Sudah kujual.”
Tubuh Thomas menegang ketika mendengar jawabanku. “Kenapa? Itu peninggalan Nenek, kan? Kapan kamu jual?”
“Sekitar tiga bulan lalu.”
“Aku enggak tahu.”
“Kamu lagi ribet dengan urusan kantor, jadi enggak ngeh ketika aku bilang mau jual semua peninggalan Nenek.” Aku berkata pelan.
Thomas bergerak gelisah di tempatnya. Tiga bulan lalu, Thomas sedang punya masalah di kantor. Ada rekannya yang melakukan penyelewengan dana dan ikut berimbas kepadanya karena mereka sama-sama membawahi sales department di regional 1 Sumatera. Thomas jadi sulit dihubungi di periode itu.
Di saat yang sama, aku mulai memikirkan apa saja yang akan kubawa ke Edinburgh. Dengan berat hati, aku menjual semua barang peninggalan Nenek. Enggak mungkin membawanya ke Edinburgh. Meskipun aku punya keterikatan emosional yang kuat dengan Nenek, enggak ada cara lain yang lebih masuk akal selain menjualnya. Aku enggak bisa meminta Mama untuk menjaganya, bagi Mama itu cuma barang yang enggak ada gunanya. Aku juga enggak enak minta tolong Dinda untuk merawatnya, dia sudah berbaik hati menyimpan buku-buku milikku, enggak perlu dibebani dengan barang antik ini.
“Kamu baik-baik saja?”
Aku menyusut air mata yang menetes turun karena toko barang antik ini hanya mengingatkanku kepada Nenek. Thomas merangkul pundakku dan membawaku keluar dari toko.
Thomas tahu aku sangat menyayangi Nenek. Sejak kecil, aku dirawat oleh Nenek. Aku enggak pernah kenal Papa, karena baik Mama atau Nenek sama sekali enggak pernah memberitahu siapa ayahku.
“Dia cuma laki-laki pengecut yang enggak pantas buat dibahas.” Itu alasan Mama.
Sementara Nenek langsung memasang wajah terluka setiap kali aku bertanya soal Papa. Jadi, aku menahan keingintahuan itu jauh-jauh. Saat tumbuh remaja, aku pernah berada di masa galau yang ingin tahu soal Papa. Sekarang aku enggak mau tahu lagi. Beliau tidak peduli kepadaku, tidak pernah mencari tahu soal aku, jadi untuk apa memikirkannya?
Aku juga enggak dekat dengan Mama. Mungkin Papa telah menorehkan luka yang sangat dalam di hatinya, sehingga Mama memilih mengabaikanku. Bagi Mama, aku bukti nyata kesalahan besar yang pernah dilakukannya.
Mama tidak pernah membuatku merasa memiliki seorang ibu. Saat aku kelas lima SD, Mama menitipkanku di rumah Nenek di Semarang sementara Mama pindah ke Jakarta dengan Om Harun, suami barunya. Om Harun bukan pria pertama yang kukenal dekat dengan Mama, tapi Om Harun yang berhasil menikahi Mama. Sayangnya pernikahan itu enggak berlangsung lama. Lima tahun setelahnya, Mama pulang ke Semarang dan menyalahkanku atas kegagalan pernikahannya.
Selalu begitu. Mama berganti dari satu pria ke pria lain, dan setiap kali hubungan itu gagal, Mama akan menyalahkanku. Bulan depan, Mama akan menikah untuk keempat kalinya dengan Om Surya, yang baru dikenalnya tiga bulan lalu. Aku belum pernah bertemu Om Surya. Kata Mama enggak perlu, karena aku bisa membawa sial. Mama enggak mau pernikahannya gagal lagi. Beruntung aku akan ke Edinburgh, sehingga Mama enggak perlu khawatir aku bisa mendatangkan kesialan untuk pernikahannya kali ini.
Hanya Nenek satu-satunya yang menyayangiku. Sayangnya usia tua merenggut Nenek dariku. Beberapa bulan menjelang lulus SMA, Nenek meninggal. Meski di atas kertas ada Mama, nyatanya aku sebatang kara.
Aku membawa serta barang tua di rumah Nenek ke Jakarta, untuk mengukuhkan kenangan antara aku dan Nenek.
Namun, kenangan selamanya hanya akan berupa memori. Kenangan dengan Nenek yang tertanam dalam barang tua itu enggak akan mengembalikan Nenek. Aku sudah tiba di satu titik di mana aku enggak bisa lagi berpegang pada kenangan, dan menjual barang-barang itu adalah caraku untuk lepas dari kenangan bersama Nenek.
Seharusnya aku enggak berada di Jalan Surabaya. Seharusnya aku enggak mengikuti permainan Thomas. Apa pun yang direncanakannya, itu hanya akan memupuk kenangan baru yang nantinya akan menghantuiku ketika sudah berada jauh di Edinburgh.
Menambah kenangan baru dengan Thomas adalah hal terakhir yang seharusnya kulakukan.
“Kamu bisa nangis, aku di sini,” bisiknya.
Aku menggeleng. “Itu cuma barang, Mas. Aku sudah menjualnya, tapi kenangan soal Nenek masih ada di hatiku.”
“Selama kamu di Edinburgh, aku akan sering-sering ke Semarang buat nengokin makam Nenek.”
Aku menggeleng. “Enggak perlu, Mas.”
Thomas meraih daguku, membuatku mengangkat wajah dan membalas tatapannya. “It’s okay. Kamu sayang banget sama Nenek, dan meski aku belum pernah ketemu beliau, aku udah kenal Nenek lewat ceritamu.”
Aku tersenyum getir. Ketika aku membuka cerita tentang masa kecilku, aku menangis sejadi-jadinya. Thomas tidak berkomentar, hanya menyediakan pundaknya sebagai tempatku menangis. Setelah tidak ada lagi air mata yang tersisa, Thomas masih memelukku.
“Sekarang aku paham kenapa kamu cukup rumit. Masa lalumu yang enggak mudah membentukmu jadi perempuan kuat seperti ini,” ucapnya waktu itu.
“Aku kelihatan menyedihkan, ya, di matamu?”
Thomas menggeleng. “Kamu … keren, Sha. Aku makin sayang sama kamu.”
Sayangnya, ucapan itu enggak bertahan lama. Mungkin Thomas masih sayang kepadaku, tapi dia tidak pernahmenunjukkannya. Apalagi mengucapkannya sebelum hari ini. Membuatku bertanya-tanya apakah sayang itu masih ada karena di semua plan yang dimilikinya, dan aku hanya sebuah objek yang bisa diselipkan di antara daftar rencana itu?
“Kalau radio ini muat, kan, di kopermu?” Thomas mengangkat sebuah radio tua yang aku enggak yakin masih bisa berfungsi dengan baik.
“Radioku masih ada.”
Nenek suka mendengarkan radio. Setiap berita dari RRI menjadi bahan obrolan dengan Nenek. Sandiwara radio adalah kesukaan Nenek. Jadi, aku mempertahankan radio butut yang sudah tidak bisa dipakai sebagai satu-satunya bukti kalau aku pernah punya kenangan manis dengan nenek.

Radio tua | ilustrasi: hipwee via www.hipwee.com
“Sorry, aku pernah menyinggung soal radiomu itu.” Thomas menimbang radio tua di tangannya.
Thomas pernah protes karena katanya kamar indekosku membuatnya sesak. Harus kuakui kalau kamarku enggak pernah rapi. Aku berdalih, sebagai freelancer, aku cukup kesulitan mengatur waktu. Deadline yang enggak kenal waktu membuatku enggak pernah sempat membereskan kamar.
“Radio butut ini kenapa masih disimpan, sih? Kamu tuh harus lebih rapi, Sha. Kalau enggak guna lagi, buang aja,” ujarnya sore itu, untuk kesekian kalinya, ketika Thomas main ke indekosku yang enggak ubahnya seperti kapal pecah.
“Itu radio nenek.”
“Terus? Emang masih bisa dipakai?”
Aku menggeleng.
“Ya udah, buang aja. Sampah tuh enggak usah disimpan.”
“Itu kenanganku dengan nenek, bukan sampah.”
Thomas tampak bersalah ketika aku membalas ucapannya dengan ketus.
“Sorry, aku enggak kayak kamu yang berkecukupan. Finansial dan kasih sayang keluarga. Kamu mungkin enggak paham kalau sampah-sampah ini punya kenangan emosional, dan satu-satunya yang bisa bikin aku waras.” Aku berkata tajam.
“Sorry, ya, Yang. I was quite insensitive.” Thomas meraihku ke pelukannya. “Tapi, kamarmu berantakan. Pantas kamu ngerasa sumpek terus menerus. Coba, deh, rapiin.”
Sore ini, ketika Thomas memberikan radio tua sebagai hadiah perpisahan, aku kembali teringat momen itu.
Thomas tidak hanya membantuku merapikan kamar, tapi dia juga membantuku untuk merapikan hidup agar lebih tertata. Thomas pernah mengemukakan ide agar aku mencari pekerjaan tetap, dia enggak bisa sepenuhnya menerima alasanku lebih nyaman sebagai freelancer, karena dengan begitu aku enggak perlu terikat kepada sesuatu.
Sayangnya, Thomas membantuku menata hidup untuk menjadi seperti yang dijalaninya. Dengan plan yang detail, juga langkah yang harus dilakukan. Thomas lupa bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan, dan dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk kejutan itu sehingga selalu mencari pihak lain untuk disalahkan ketika rencananya berantakan karena kejutan yang diberikan oleh hidup.
Thomas menyayangiku, dan sekarang kusadari kalau caranya menyayangiku hanya membuatku ingin menjauh darinya.
-Bersambung-
Baca bab selanjutnya: A Trip Down Memory Lane – Chapter 5: Love is Not Always About a Compromise

Artikel Bermanfaat dan Menghibur Lainnya
Tim Dalam Artikel Ini
Eks jurnalis dan sekarang menjadi content development di salah satu aplikasi. Mulai menulis di Wattpad sejak 2017 dan beberapa karya bisa dibaca di platform menulis online atau buku. Hubungi di @revelrebel_ (instagram) dan www.revelrebel.id