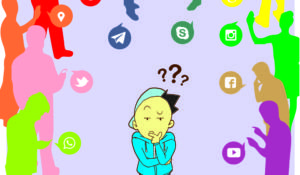Orang tua memang menyebalkan. Sejarah sudah mengemukakan jika setiap generasi rasanya selalu merendahkan generasi yang lebih muda. Selalu, memang. Sama seperti kita yang doyan ceriwis ke adik-adik yang masih kita anggap ingusan. “Kasihan ya anak zaman sekarang, mainnya sama gadget melulu, nggak kenal asyiknya Eva Arnaz main gundu.“
Apa benar kasihan? Padahal lahir-batin mereka mungkin bahagia kok. Kita saja yang tidak sadar diri jika dulu juga dibegitukan oleh orangtua kita,”Kasihan ya anak zaman sekarang, nggak kenal serunya deg-degan ditembaki militer di jalanan cuma gara-gara pakai tato atau pernah nongki-nongki bareng preman pasar.”
Masing-masing dari kita semua sejatinya hanyalah kids zaman now bagi generasi sebelumnya.
Senioritas mendarah daging bersamaan bertambahnya usia. Pemuda bukan cuma dipandang remeh bak rempeyek, namun juga dimanfaatkan sedemikian rupa. Makanya kita senantiasa dijauhkan dari kesempatan mengambil keputusan. Coba lihat pemegang kekuasaan (baca: elit partai /pejabat negara), kebanyakan isinya om-om buncit yang kenyang kepentingan. Celakanya, kita pasrah saja diasingkan lewat gaya hidup konsumtif atau disesatkan dengan kebanggaan atas ketidaktahuan.
Padahal sejarah juga sudah mengemukakan jika cuma anak muda yang sanggup membuat perubahan.
Tadinya saya sudah ancang-ancang akan cerita panjang lebar perihal keterlibatan kaum muda di sejarah Indonesia. Tapi ini masih momen Sumpah Pemuda, jadi niscaya sudah berbondong-bondong media yang bikin konten tentang itu. Daripada mengulang-ulang dan bikin ngantuk, saya langkahi saja. Setidaknya kamu sudah pernah dengar Budi Utomo, Peristiwa Rengasdengklok, Penjungkalan suharto (s-nya kecil, yes!) di tahun 1998, dan… ah, saya rangkum saja dengan mengutip wawancara terakhir—kebetulan dengan majalah Playboy dan Happy Salma, waduh—dari Pramoedya Ananta Toer:
”Saya percaya, sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda. Angkatan tua itu jadi beban.”
.
.
.
Lalu sejak kapan anak muda jadi lemah gemulai begini???
Sejak suharto menyerang.
Dengan sangat taktis, pemuda di zaman Orde Baru dikonstruksi ulang. Dari era inilah kita kenal istilah “remaja”. Dalam Solo in the New Order, antropolog bernama James Siegel menukaskan bahwa “remaja” punya selera dan aspirasi tertentu yang dibentuk beda dengan “pemuda”. Kamu pasti bisa ‘kan membedakan kesan istilah “pemuda” dan “remaja”? Mendengar kata “pemuda”, kita jadi ingat demonstrasi, idealisme, tekad baja, pekik kemerdekaan, Soe Hok Gie, dan sebagainya. Sementara apa kesan yang keluar dari kata “remaja”? Pacaran, tawuran, seks bebas, rental playstation, Bastian Steel, dan segala saripati Si Boy Anak Jalanan. Miriz, pakai “z”.
Selain sengaja dibentuk, anak muda zaman sekarang cenderung abai dan apolitis juga karena pemerintahannya porak poranda. Sedari belajar membaca koran atau menonton berita, kita jadi saksi bagaimana menjenuhkan dan tidak tahu malunya jagat politik. Imajinasi terhadap kata “politik” hampir sama dengan imajinasi pada kata “Yolanda”. Nista dan tercela. Politikus adalah profesi (?) paling antagonis di semesta raya. Walau sebenar-benar-benarnya sama-sama penuh tipu muslihat dan harapan palsu, tapi panggung entrepreneur atau pentas pencarian bakat idol-idol itu jauh lebih menarik bagi kawula muda daripada ajang politik. (Hebatnya, Anang Hermansyah dan Ahmad Dhani mencoba semuanya.)
Memangnya sepenting apa anak muda harus peduli dengan politik?

Merebut reformasi via arsipindonesia.com
Setidaknya ada tiga jenis anak muda dalam relasinya dengan kesadaran politik. 1) Mereka yang sadar politik. 2) Mereka yang apolitis. 3) Mereka yang tidak tahu tapi merasa tahu.
Jelas bahwasanya golongan pertama adalah varietas unggul sementara golongan ketiga harus dibasmi sekarang juga. Bagaimana dengan yang kedua? Problemnya, tidak mungkin untuk seseorang dalam sebuah masyarakat benar-benar lepas dari politik. Menurut Aristoteles, politik dalam esensinya adalah upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kebijakan politik berdampak dan melibatkan seluruh aspek kehidupan kita.
Contoh sederhana, kita semua punya suara dalam pemilu. Golput bukan berarti netral. Mau tidak mau kita sudah terikat dalam pemetaan perebutan kuasa. Salah satu—dari sekian banyak—asumsi tentang terpilihnya Donald Trump menjadi presiden adalah karena banyak generasi muda Amerika Serikat yang memilih golput. Padahal arek-arek ini adalah batu penarung terbesar Trump. Mereka punya personalitas yang cenderung lebih alergi dengan tabiat dan janji-janji Trump, tapi sayangnya mereka ternyata juga tidak mau mendukung kompetitornya. Durian runtuh untuk Trump dan tim suksesnya tahu itu.
Di pemilu 2014 kemarin pun situasinya sebelas-duabelas. Sebagai orang Jogja, kuliah sosial politik di UGM, dan mesra dengan dunia seni-budaya, latar belakang saya adalah tipikal pemilih Jokowi. Jika saya golput, secara tidak langsung saya memberikan suara pada Prabowo. Lalu saya memilih siapa kemarin? Rahasia, kepo banget lu kayak registrasi SIM Card.
Oh, tapi sebenarnya artikel ini bukan bermaksud mengecam mereka yang golput-minded atau menjadi imbauan anti-golput yang naif. Bukan, bukan. Golput adalah sebuah hak dan silakan sesilakannya asal kamu tahu konsekuensinya. Golput tidak mentah-mentah sama dengan apatis dan putus asa, tapi bisa jadi manifestasi sikap politik tertentu. Lagipula apakah gelaran pemilu benar-benar mewakili cita-cita demokrasi? Ah, justru keraguan ini adalah contoh dari sebuah kesadaran politik, dan itulah yang utama dan krusial sesungguhnya.
Kesadaran politik yang saya maksud adalah penguasaan wawasan, ketajaman analitis, dan pengendalian emosi. Tujuannya untuk menuntunmu secara rasional menentukan keberpihakan dalam konflik kekuasaan dan cara bijak untuk mengartikulasikannya.
Ini mengembalikan amatan kita pada kategori ketiga dari penggolongan anak muda di paragraf lalu, yakni “Tidak tahu tapi merasa tahu.” Sialnya, ini diperuncing dengan fakta bahwa generasi millennial memang punya watak yang lebih vokal dan doyan berekspresi di dunia maya. Mulai mengumbar isu yang teramat personal (dan tidak ada yang perlu peduli) sampai yang (sadar atau tidak) merugikan orang banyak.
Dalam dinamika politik modern, tak ada peranti yang punya daya penetrasi dan dampak melebihi media massa. Efektivitas dan efisiensinya semakin di depan. Di zaman orde baru, cukup menunggangi TVRI dan stasiun televisi lain untuk memenangkan segalanya. Kini, media sosial adalah medan tempur yang sesungguhnya. Ring tinju politik yang hakiki. Dan anak muda adalah yang paling banyak berdenyut di dalamnya.
Masalahnya, para muda-mudi millenial ini hanya menguasai mediumnya tapi tidak dengan wacana yang dihidupi olehnya. Kita hafal di luar kepala teknik mengedit foto, tapi gagap terhadap apa buntut dari editan foto yang bergulir menjadi kampanye hitam. Begitu rentan anak muda dijadikan pion atau boneka perebutan kekuasaan, serta enteng dikontrol dan digiring untuk membenci atau mendukung sesuatu. Kerbau saja sudah bosan dicocok hidungnya. Kita kehilangan kepekaan skeptis, kritis, dan rasional yang ditutup oleh kepercayaan buta. Bahkan, kadang fanatisme ditanam dalam-dalam sehingga kita gencar membagikan atau bersuara hanya untuk menegaskan identitas kita. Menjatuhkan A agar kita terlihat sebagai B, atau menjatuhkan B agar semua teman-teman sekelas tahu kita adalah A. Fitnah hilir mudik laksana lagu “Akad”.
Kita adalah aktor secara literal. Tampil terdepan, tapi sejatinya hanya bergerak di bawah kehendak sutradara. Seperti kata Soe Hok Gie “Pemuda kita itu umumnya hanya mempunyai kecakapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris menerima perintah menyerang, menyerbu, dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin” Waduh, pedas, Bang.
Saatnya mengembalikan anak muda sebagai subjek, bukan lagi-lagi objek

kritis sejak dini via arsipindonesia.com
Ada sebuah teori gampang-gampang susah, namanya Teori Kemungkinan Elaborasi. Ini adalah teori yang mencoba menganalisis kemungkinan seseorang untuk terbujuk oleh pesan. Ada dua rute untuk pengolahan informasi, yakni rute sentral dan periferal. Elaborasi atau berpikir secara kritis terjadi pada rute sentral, sementara ketiadaan berpikir secara kritis terjadi pada rute periferal. Seseorang yang mengolah informasi lewat rute sentral akan memikirkannya secara aktif dan merespons dengan berhati-hati. Sementara seseorang yang mengolah informasi lewat rute periferal akan menerimanya mentah-mentah dan asal-asalan.
Nah, kemampuan kritis yang diterapkan pada setiap informasi bergantung pada faktor motivasi yang sedikitnya terdiri dari tiga hal. Pertama, keterlibatan atau relevansi dengan topik. Kedua, jumlah perbedaan pendapat (semakin beragam pendapat akan membuat kita lebih hati-hati menerima informasi). Ketiga, kecenderungan pribadi terhadap cara berpikir kritis.
Syahdan, algoritma media sosial yang terkutuk itu membuat sentimen linimasa kita cenderung seragam, sehingga kita jarang melihat perbedaan pendapat. Seakan-akan yang ramai di linimasa kita selalu adalah kebenaran. Padahal kalau kamu anti-Indomaret, ya memang linimasamu akan ditebari status-status dari pendukung Alfamart. Begitu juga sebaliknya. Pandangan kita terhadap dunia cenderung bias dan sesat.
Karena itu kita perlu lebih melibatkan diri dengan topik. Pendidikan politik dan khazanah pengetahuan sejarah perlu dikejar supaya kita memahami relasi-relasi sosial yang ada di masyarakat. Tidak harus hafal nama menteri atau anggota DPR yang korupsi (terlalu banyak juga, mubazir ingatanmu). Yang utama adalah kita mampu membaca situasi-situasi rasis, fasis, akar sebuah permasalahan sosial, dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam setiap kebijakan. Membuka diri terhadap ilmu politik membimbing kita untuk menemukan bahwa moral tidak selalu adalah solusi, nasionalisme tidak harus selalu harga mati, isu komunisme adalah kecemasan yang dibuat-buat, dan bahwa banyak isu-isu agama-etnis yang muasalnya tetap kembali pada perkara ekonomi atau rebutan tanah.
Menurut data Badan Pusat Statistik, demografi Indonesia akan melonjak pada rentang waktu 2020-2035 sekitar sebesar 305,6 juta jiwa dengan persentase angkatan kerja produktif dari generasi millenial mencapai 66,6 persen. Praktis, keberpihakan generasi millenial akan diperebutkan. Intrik-intrik akan merebak, termasuk isu-isu agama, etnis, dan nasionalisme. Sebuah pertaruhan apakah kamu nanti menjadi korban atau kaum mujur yang punya otoritas dalam menaruh sikap politisnya.
Saatnya kita berhenti menjadi objek yang selalu dipolitisir. Saatnya kita menjadi subjek. Menjadi barisan yang sadar untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan koreksi-koreksi terhadap pemerintah. Kita harus punya sikap untuk mengatakan tidak dari apa yang diarahkan kepada kita. Sebuah upaya memerdekakan diri untuk lebih jernih menentukan keberpihakan. Apalagi sekarang sedang musim adu domba.
Padahal politik bukan Tinder. Kita tidak cuma bisa swipe kiri atau kanan.
Makanya jangan menunggu harus jadi bapak-bapak sarungan ngopi sambil baca koran untuk punya minat dengan politik atau persoalan masyarakat. Toh politik tidak melulu berkaitan dengan birokrasi, pencitraan, dan suap menyuap. Pun menyukai politik tidak berarti harus selalu menjadi politisi. Kamu bisa menjadi tukang sablon yang sadar kelas sosial, pegawai Alexis merangkap aktivis HAM, hingga penulis yang suka lupa kalau pembaca Hipwee nggak suka politik.
Yah, tapi siapa tahu…